
Mundur

Richard Lloyd Parry dalam bukunya In Time of Madness menyebut bahwa akhir dari orde baru terasa seperti seks tanpa orgasme. Momen yang seharusnya menjadi titik tolak dari pangkal segala kebobrokan negara selama lebih dari tiga dasawarsa menjadi kisah yang melempem. Titik itu berlangsung alakadarnya, sangat biasa, dan antiklimaks. Dalam nada yang lebih pahit, ia menyebut momen tersebut sebagai momen historis yang paling tidak bermomentum.
Bukan hal aneh jika Richard mendaku demikian. Pasalnya, medio 1998 terjadi kelindan air mata, darah, dan keringat yang tak habis-habis mengucur. Kala itu, masyarakat Indonesia lebih berani berada di jalan-jalan utama untuk bersitegang dengan Pemerintahan Soeharto. Hampir semua tempat menjadi muara kemarahan dan frustrasi yang terperam selama puluhan tahun dalam rendaman opresi.
Di Jakarta, penjarahan terjadi di mana-mana. Simbol-simbol penindasan dan ketidakadilan adalah sasaran utama para pemarah ini. Tempat perbelanjaan mewah yang penuh dengan barang yang harganya tak terjangkau, etalase mobil dan motor, rumah-rumah para pendukung Orde Baru, hingga gedung-gedung pemerintah tempat praktik kongkalikong menjadi sasaran pelampiasan mereka.
Kemarahan yang ditimbun selama bertahun-tahun membuat perusakan kota, penjarahan, kerusuhan, hingga pembunuhan terjadi. Di sisi lain, keterpurukan kota membangun kekuatan baru. Kekuatan untuk menyatakan pendapat. Kekuatan untuk menyeru mundur kepada seorang despot. Akademisi, jenderal, politisi, dan profesi lain bergabung menyulut api di lumbung kekuasaan Soeharto. Ketegangan makin mengangkasa ketika nyawa-nyawa meregang.
Api kemarahan kian lama kian membesar. Tentara sudah berjaga-jaga. Desakan mundur didengungkan keras-keras. Soeharto berada di ujung tanduk. Meskipun semua tuntutan tadi akhirnya dijawab dengan kemunduran Soeharto, pidato pengunduran dirinya bergulir antiklimaks. Selama 293 detik paling menentukan itu, Soeharto membaca kata demi kata di atas naskah pidatonya dengan terlalu tenang. Pengunduran diri Soeharto dan pengambilan sumpah presiden baru terjadi hanya dalam kurun waktu 8 menit saja. Dalam waktu secepat itu, presiden telah berganti, pemerintahan baru terbentuk, dan rakyat terbengong-bengong. Perpindahan kekuasaan berjalan terlalu mulus. Dan yang paling tidak meyakinkan, kemunduran diri Soeharto terasa seperti sebuah perintah. Perintah dari Soeharto sendiri.
Tujuh belas tahun kemudian, di sisi lain Jakarta, seorang lelaki juga mundur dari jabatannya. Namanya Sigit Priadi Pramudito. Ia mundur dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak, jabatan yang prestisius di era sekarang.
Berbeda dengan Soeharto, kemunduran Sigit terkesan tiba-tiba. Meskipun Sigit bertukas bahwa rencana kemunduran dirinya sudah ia persiapkan sejak lama, namun gelagat mundur tidak pernah terdengar darinya. Tidak ada isyarat untuk meninggalkan jabatan tersebut, terlebih karena Ia baru saja dilantik pada awal tahun ini.
Sigit mundur sebagai pertanggungjawaban atas kegagalan institusi yang dipimpinnya memenuhi target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sebesar Rp 1294 triliun dirasa tidak akan tercapai. Bahkan Sigit berkata bahwa proyeksi realisasi penerimaan hanya mencapai 80-82%. Nilai tersebut masih kurang dari realisasi penerimaan yang dapat ditoleransi sebesar 85%.
Keberanian mundur dari jabatan adalah sebuah tindakan ksatria. Kalimat ini muncul dan berhamburan dalam sepekan terakhir menyambut pengunduran diri Sigit. Media massa menyambut Sigit sebagai sebuah contoh pejabat yang berani memikul tanggung jawab atas kekalahan menyeluruh pegawai-pegawainya. Di negeri yang konon miskin panutan ini, tindakan tersebut diapresiasi tinggi-tinggi.
Mari kita kesampingkan dahulu geliat emosional yang hadir dalam momen mundurnya Sigit dan Soeharto. Ada seutas tali yang mengubungkan figur Sigit dan Soeharto, yaitu ke-Jawa-an. Sigit berasal dari Purwokerto, sedangkan Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Bantul.
Dalam kisah Jawa Kuno, seorang raja yang mendekati akhir hayatnya akan menarik diri dari kehidupan nun ramai. Ia pergi ke tempat yang jauh dan keramat. Ia tidak mati, namun pergi melenyapkan diri. Moksa, begitu nama peristiwa tersebut. Moksa dilakukan untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Dalam tradisi Hindu, moksa memutus putaran reinkarnasi. Pelaku moksa lalu hidup dalam keabadian.
Sigit dan Soeharto, sebagai orang yang mengambil keputusan untuk turun, seperti melaksanakan tetirah para Raja Jawa Kuno tersebut. Sejatinya, mereka tidak mundur atau turun tetapi mengalami sebuah peristiwa kenaikan. Mundur untuk menang. Turun untuk naik. Mereka seakan-akan melakukan moksa, meninggalkan gelanggang yang riuh untuk kembali melakukan kegiatan sunyi dan penuh sikap berserah diri. Dan moksa adalah sebuah laku paripurna pemimpin yang gilang gemilang dalam pemerintahannya, seperti laku yang dilakukan oleh Para Pandawa dalam akhir Mahabharata. Namun, benarkah demikian?
Sikap berserah diri adalah bagian integral dari moksa. Maka, moksa lebih terkait dengan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan daripada hubungan horizontal dengan sesama. Oleh karena itu gagasan moksa, menurut Soemarsaid Moertono, membuat gagasan tentang perubahan menjadi terlepas dari pengaruh upaya manusia yang dangkal dan diwarnai oleh takdir Tuhan yang tak terelakkan.
Seseorang harus mengerti sejauh mana mereka dekat dengan akhir hayat sebelum memutuskan untuk menjalankan moksa. Sigit serta Soeharto tampaknya juga merasa bahwa hayat jabatan mereka akan segera habis setelah menemui tanda-tanda tertentu.
Soeharto merasakan keterdersakan ketika secara nyata menghadapi pembakaran, penjarahan, dan kerusuhan di seantero Indonesia. Krisis ekonomi dunia ditambah rubuhnya kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan ambruknya keamanan nasional. Waktu di Jakarta diukur dari demo ke demo. Kekacauan adalah halaman negeri ini. Situasi semakin riuh setelah parlemen turut meminta Soeharto untuk mundur.
Sementara itu, Sigit juga merasakan posisinya berada di ujung tanduk kala banyak pihak mengadilinya. Prediksi shortfall yang semakin besar membuat celah yang lebar antara target dan realisasi. Selain itu, langkah strategis darinya terbentur kondisi perlambatan ekonomi. Pilihan yang harus direguk olehnya adalah insentif pajak besar-besaran agar ekonomi Indonesia tetap menggeliat. Pilihan yang membuat usaha mengejar target makin meleset. Realisasi yang meleset ini membuat beberapa pihak sempat mendesak Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mencopot Sigit, namun Menteri Keuangan menolak.
Di tengah keadaan yang mereka hadapi, Sigit maupun Soeharto membuat pilihan mundur nampak begitu logis. Keduanya pun sama-sama mengundurkan diri. Namun, terdapat perbedaan kentara dari perjalanan kedua orang ini.
Dalam konsepsi Jawa Kuno, kekuasaan tidak memiliki komponen moral dan etika. Kekuasaan bukan perkara sah atau tidak sah. Terkait dengan konsep Raja sebagai “Paku Bumi” yang menyelaraskan apa yang tampak dan tidak tampak, kelemahan dalam daya cengkeram kekuasaan adalah tanda-tanda jatuhnya seorang penguasa.
Seorang penguasa yang sekali saja pernah membiarkan kekacauan alam -banjir, letusan gunung api, dan wabah- dan sosial -pencurian, kerakusan, dan pembunuhan- muncul akan menemukan kesulitan besar untuk menegakkan kembali otoritasnya. Ben Anderson menulis bahwa Orang Jawa cenderung percaya bahwa jika seorang raja masih memiliki kekuasaan maka kekacauan itu tidak akan pernah muncul.
Merunut konsepsi tersebut, Soeharto jelas-jelas sudah layak untuk jatuh karena kekacauan sosial sudah terjadi. Namun, kekacauan tidak terjadi pada waktu Sigit terdesak. Turunnya realisasi penerimaan bukan hanya disebabkan kinerja yang kurang baik dari armada yang dimiliki Sigit, melainkan resultan dari banyak faktor yang berperan lebih besar.
Oleh karena itu, mudah saja melihat perilaku Soeharto kala meninggalkan piramida patronase pemerintahannya sebagai pencitraan untuk moksa belaka. Konsepsi Raja Jawa yang berusaha ia ambil terlihat mentereng di permukaan lewat kesan “kelegawaannya mundur” ketika meminta parlemen segera menyumpah BJ. Habibie “saat itu juga” lewat penutup pidatonya. Ia berusaha keras melumurkan imaji bahwa ia berhasil menjaga Indonesia dari kekosongan pemerintahan meskipun mundur, sehingga kepergiannya layak disebut moksa. Padahal, pemerintahannya berlumur kekalutan sosial. Dosa-dosa yang ia ciptakan menggurita terlalu tebal hingga sulit untuk dibersihkan sampai sekarang.
Namun Sigit, dengan bermacam-macam alasan yang dapat didaku sebagai apologi apabila penerimaan pajak tercapai, lebih memilih mundur. Sigit hanya merasa gagal. Titik. Padahal, Ia tidak mutlak salah. Pemakluman atas shortfall realisasi penerimaan sudah sering disebut. Kebijakan yang dikeluarkan juga sudah optimal. Target yang jauh juga telah Ia kejar sekuat tenaga. Tapi apa lacur, mungkin Sigit lelah, seperti kata para generasi millenial. Lelah membawa beban APBN atau lelah didesak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan non revolusioner.
Di ujung kepemimpinannya, Sigit hanya menyampaikan pesan pendek. Ia mohon maaf atas kegagalannya. “Nya”, bukan “kami”. Ia melimpahkan kesalahan musabab kegagalan kepada dirinya sendiri, bukan orang lain. Sigit melepaskan jabatannya karena itu.
Maaf dan pertanggungjawaban dari Sigit menjadi pembeda ketika Soeharto menyebut kata “maaf” sebagai pemanis belaka dalam pengunduran dirinya. Pidato pengunduran diri yang tengik itu terlebih dulu berbicara soal “tidak adanya tanggapan yang memadai” atas “rencana pembentukan komite reformasi” demi “memulihkan situasi nasional” yang merupakan idenya. Soeharto, dalam nadanya yang tenang, sibuk menunjuk orang-orang sebelum mengaku ikut berkubang dalam kesalahan. Pengunduran dirinya, kata Richard Lloyd Parry, membuat kekalahan yang ia derita merampas seluruh rasa kemenangan musuh-musuhnya.
Hiruk pikuk kemunduran Sigit Priadi Pramudito telah lewat. Mungkin, dengan tidak ia sadari, Sigit sedang menjalani laku moksa. Melepaskan segala kelelahan, melupakan segala keriuhan. Mungkin Sigit sudah merasa paripurna. Dan kita kelak akan merasa: dalam estafet kemudi institusinya tak ada keriuhan atau suara-suara kemenangan, hanya kehilangan sosok panutan. Seorang Pria Jawa yang pergi melakukan moksa.
Related
Sunyi Menyanyi pada Pagi

Gula Kacang
You May Also Like

Memburu Durian, Mencumbu Keaslian dari Indonesia
22/02/2018
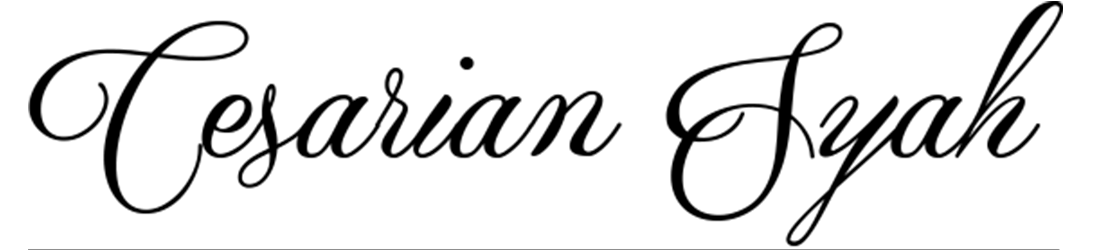
118 Comments
Slamet Rianto
Keren tulisan dan alur berfikirnya, Mas..
Salam.
Meidiawan Cesarian Syah
Terima Kasih, Pak Slamet. Salam kenal…ini masih belajar di bawah asuhan Mz Topiq dan Mz Gita~
Pradirwan
manstap mas… salam kenal
Meidiawan Cesarian Syah
Salam kenal Mas Pradirwan