Mengerat Senja di Pelabuhan Sunda Kelapa

Matahari belum surut dan sore belum begitu rapi waktu saya beranjak ke arah utara. “Kalau Jakarta sedang tidak panas dan jalanan juga sedang tidak ramai, pergilah ke Pelabuhan Sunda Kelapa”, kata seorang teman. Ia mengucapkannya beberapa bulan lalu. Tetapi, baru sore ini saya bisa menggelandang diri ke sana. Kebetulan, hari sedang libur dan sengatan matahari seperti remaja yang kali pertama berkasih-kasihan: hangat dan malu-malu durjana.
Saya pergi dengan beberapa teman. Bersama mereka, saya membelah jantung ibukota yang, entah kenapa, minim sekali sifat keibuannya. Ibu macam apa yang selalu menyediakan macet pada siang hari dan balap liar pada malam hari?
Pada siang menjelang sore itu, mobil kami terus menderu di atas tol dalam kota Jakarta yang berdebu. Untuk menuju Pelabuhan Sunda Kelapa, jalur yang paling mudah diingat ialah melalui Museum Bahari dan titik nol kilometer Jakarta. Dari sana, saya menuju ke arah utara dan berjingkat di sela-sela jalan kecil.
Kamu harus pebih peka untuk meraba letak Pelabuhan Sunda Kelapa. Soalnya, ia tidak mencolok. Kami pun sempat bingung sebelum menemukan pintu masuk. Farchan, si sopir, hampir menggabrus pagar Pintu I karena mengira di sanalah letak pintu masuk. Untung teman-teman lain mengingatkan -walau tanpa memintanya untuk mengulang syahadat – kalau ia sedang berpuasa sehingga menahan hawa nafsu, terutama untuk tidak menggabrus benda secara sembarangan, adalah sebuah keharusan.
Pintu II, yang menjadi pintu masuk untuk umum, terletak sedikit memutar dari pagar yang hampir dilumat tadi. Untuk masuk, kami cukup menebus biaya parkir dengan selembar uang bergambar Tuanku Imam Bondjol. Iya, Imam Bondjol yang memimpin pembantaian di tanah Batak itu.

Begitu melewati pintu, kami langsung merasakan nuansa yang berbeda dari kebanyakan pelabuhan. Tidak ada sembribit angin yang menyambut. Pun awak kapal yang bekerja dengan riuh. Mungkin karena saat itu adalah perpaduan antara bulan puasa, akhir pekan, serta siang yang hampir berganti senja, pikir saya, sehingga Pelabuhan Sunda Kelapa pun menjadi sebegitu lengangnya.
Tetapi sebenarnya sejak awal abad ke-19 pun, Pelabuhan Sunda Kelapa lebih akrab dengan keheningan dibandingkan keramaian. Kejayaan yang pernah ia rengkuh kala pertama didirikan kian lama kian pudar akibat pendangkalan air di daerah sekitar pelabuhan. Kapal dari tengah laut pun kesulitan berlabuh.
Padahal, potensi yang ada di depan mata saat itu tidak main-main: Terusan Suez yang baru saja dibuka. Kapal-kapal akan semakin banyak datang dan ekonomi bisa berkembang luar biasa. Sayangnya, peluang itu lolos dan Sunda Kelapa menjadi sebuah kejayaan yang disia-siakan.
Pemerintah Kolonial juga akhirnya memilih semenanjung lain di utara Jakarta untuk dijadikan pelabuhan baru. Sejarah kemudian mencatat pelabuhan baru ini lebih berkembang secara luar biasa dan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Namanya: Tanjung Priok.
Bagaimana dengan Pelabuhan Sunda Kelapa? Sekarang, ia hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia, meliputi pengemasan dan pengiriman barang.
Sore itu, saya menemukan deretan motor yang hendak dikirim, juga gelondongan kayu dan semen-semen yang sedang dibongkar muat. Barang-barang itu masih menunggu nasib akan dikirimkan ke mana: Sumatera, Kalimantan, atau pulau lainnya.


Sekali dua, lewat beberapa orang yang menjajakan aneka penganan dan minuman untuk berbuka. Ada juga yang menawarkan jasa tumpangan untuk mengelilingi dermaga dengan perahu kecil miliknya.
Selain itu, nyaris tidak ada aktivitas lain di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hanya debu dan kepulan asap yang makin lama makin banyak.
Saya tidak tahu apakah Sunda Kelapa akan sama sepinya pada hari kerja. Yang jelas, sisa-sisa keriuhan pelabuhan yang memiliki narasi hingga 15 abad hampir sepenuhnya hilang. Tak ada lagi keramaian dari pedagang Cina, India dan Timur Tengah yang membawa porselin, kain sutra dan barang lain untuk ditukarkan dengan rempah-rempah seperti pada masa kerajaan Sunda Pajajaran sekitar abad ke 12. Tak ada pula kapal-kapal Portugis yang membawa logistik seperti pada awal abad ke-15.
Keramaian-keramaian itu lambat laun lenyap di usia Jakarta yang mencapai angka 490. Sunda Kelapa tak lebih dari dermaga tua yang terengah-engah dan sekarat. Kalau tidak ada manusia di kapal-kapal yang bersandar, Sunda Kelapa sulit dibedakan dengan makam dari kapal yang karam.
Saya mencoba mengambil napas. Udara yang saya hirup sama sekali tidak asin seperti tipikal udara laut pada umumnya, walau ia tetap tajam dan kering. Bau karat jauh lebih terasa. Bukan dari kapal-kapal tua, melainkan dari kontainer, jangkar, dan besi-besi tempat memancang tali. Begitu juga bau asap dari truk-truk dan alat berat yang melintas.

Saya menelusuri gigir pelabuhan seperti Chairil menelusurinya lebih setengah abad silam -yang membuatnya menulis puisi Senja di Pelabuhan Kecil itu-. Bedanya, saya tidak membayangkan Sri Ayati, juga tidak sedang kasmaran. Saya hanya sibuk mengagumi sekujur dermaga.
Soalnya, lanskap yang digelar amboi betul. Apalagi sinar matahari sedang berwarna emas dan tidak menerjang dengan galak. Kala langit sudah mengenakan sore dengan cantik, Pelabuhan Sunda Kelapa menyediakan gambar-gambar terbaik yang sangat siap untuk dirampok dengan kamera.


Warna karat yang berumah dan bersekutu dengan kelupasan cat-cat kayu di kapal memberikan romantismenya sendiri. Belum lagi jika kamu berani melintasi papan kayu yang membawamu masuk ke dalam kapal. Pemandangan yang bisa kamu ambil pasti jauh lebih mesra. Pemandangan yang konon akan mendekatkanmu dengan visualisasi puisi Senja di Pelabuhan Kecil-nya Chairil: “Kapal, perahu tiada berlaut/menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut//”


Saya, bersama teman-teman saya, pun turut merampok gambar. Foto deretan kapal yang bersandar, barisan kontainer, hingga kontradiksi antara kapal kayu tua dan bangunan apartemen Pluit Sea View yang ada di belakangnya berhasil saya renggut dan simpan dalam gambar. Saya pun mengambil gambar teman saya yang punya misi menjadi terkenal di mana-mana.



Kesemua itu saya lakukan karena mungkin, suatu saat, aktivitas bongkar muat di sini akan lenyap jua. Ditambah dengan adanya rencana reklamasi, bukan tak mungkin Pelabuhan Sunda Kelapa akan dialihfungsikan menjadi kawasan situs sejarah melengkapi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di sekitarnya seperti Museum Bahari, Museum Fatahillah, dan Museum Wayang.
Ketika hal itu terjadi, mungkin saya akan mengenang Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat yang dikirim dari masa lalu. Atau ia akan menjadi sedemikian modernnya sehingga sejarah yang dipahat di sana adalah sejarah yang artifisial. Sehingga, untuk menikmatinya, saya harus mengirimkan diri saya kembali ke masa lalu melalui gambar-gambar yang telah saya tangkap tadi sambil merasa, mengutip kembali Senja di Pelabuhan Kecil, “masih pengap harap/ sekali tiba di ujung/ dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat/ sedu penghabisan bisa terdekap”.
semua gambar diambil menggunakan Fujifilm XA-2 dengan lensa kit XC 16-50 mm.
P.S.: tentang Tuanku Imam Bondjol, bisa dibaca di buku Tuanku Rao karya Mangaradja Onggang Parlindungan
bonus gambar: foto-foto orang-orang yang asyik menjadi model


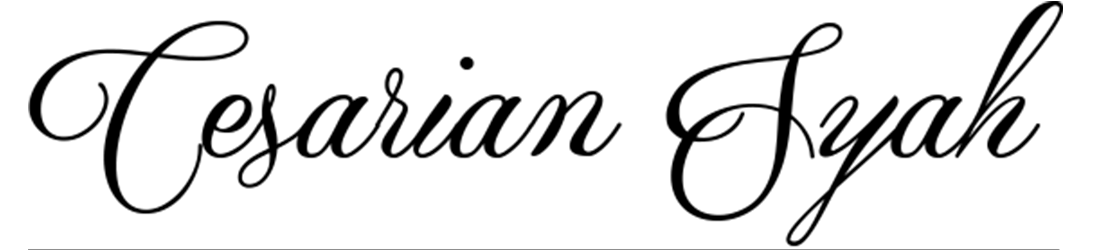
920 Comments
Meidiawan Cesarian Syah
hihihi segera mbak ke Sunda Kelapa selagi sepi. Nanti kalau ramai atau tutup malah jadi ga seru sama sekali. Mampirlah dan, jangan lupa, foto-foto.