
Drama Pascaapokalips di I Think We’re Alone Now
Hidup pascakiamat mungkin akan berada pada dua pilihan. Kamu bisa meratap atau memulai segalanya kembali dari awal. Kamu bisa jadi merasa sendirian karena tidak ada siapapun tetapi tidak menutup kemungkinan pula kalau kamu juga bakal merasa merdeka karena alasan yang sama.
Dua pilihan itu agaknya ada di depan kedua bilah mata Del (Peter Dinklage) dalam I Think We’re Alone. Berlatar di sebuah kota pinggiran New York pascakiamat, hari demi hari Del dimulai dengan datang dari rumah demi rumah. Mendapati kenyataan kalau ia bisa jadi adalah manusia terakhir di muka bumi, ia pun mencari barang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, juga baterai.
Setelah itu, ia mencabut foto-foto pemilik rumah dari bingkai yang mereka pajang. Membungkus jenazah yang berada di dalam rumah untuk dikuburkan adalah hal terakhir yang Del lakukan sebelum menghabiskan sisa hari dengan memancing atau menata ulang perpustakaan tempatnya bekerja, juga tinggal.
Aktivitas ini dilakukan oleh Del saban hari dan membuat kita mengira ini adalah bentuk rutinitas yang serupa meditasi. Del, dalam kesendirian dan kesunyiannya, tidak tampak menderita. Baginya, sendiri bukanlah masalah. Ia bukan seseorang yang takut jika esok tidak pernah datang. Pun, ia adalah ejawantah dari keteraturan dalam dunia yang kaotik. Pengulangan-pengulangan ini membuat setengah jam pertama film adalah momen sinematik yang indah, meskipun semesta yang disajikan di dalamnya sungguh gelap
Momen-momen keteraturan yang sudah dinyalakan Del lalu goyah ketika seorang gadis bernama Grace (Elle Fanning) datang dengan mengendarai mobil. Del, yang menemukan Grace pingsan setelah mobil yang ia kendarai menabrak tiang, kemudian menghadapi pilihan sulit: apakah ia akan membiarkan Grace tinggal atau menyuruhnya pergi. Di satu sisi, ia sudah menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri sementara di sisi lain, ia tidak bisa menutup pintu kesempatan untuk mendapatkan lawan bicara semudah itu.
Setelah fragmen ini, keteraturan yang ditanamkan di awal-awal tadi runtuh dan membuat I Think We’re Alone Now menjadi film yang menebarkan gejala paranoid, adu sikap yang kontras, dan permasalahan baru lainnya. Del yang tadinya santai saja menghadapi kepunahan peradaban manusia, pun harus merelakan emosinya terkuak dan terbuka lebar saat berkomunikasi dengan Grace.
Kemudian, dialog-dialong di antara keduanya menjadi sebuah deskripsi bagaimana dua orang dengan watak yang sangat berbeda, pun jika kita hendak menganggap perbedaan fisik juga lewat kontradiksi antara Del yang memiliki dwarfisme dan Grace yang semampai, harus berjalan beriringan dalam suatu bahasa penyintas yang universal. Grace tidak punya pilihan lain untuk menghadapi Del, begitupun sebaliknya. Mereka saling menjajal karakteristik lawan bicaranya hingga mendapati frekuensi yang sama.
Percik-percik pertikaian dan kontradiksi relasi ini membuat I Think We’re Alone Now menjadi film yang emosional. Del adalah orang yang lebih merasa kesepian ketika orang-orang lain di kotanya masih hidup, sedangkan Grace adalah si ceriwis yang gejolak masa mudanya belum tamat. Perbincangan, baik dalam nada yang gegap gempita maupun nuansa yang amat lirih adalah kesenjangan yang subtil.
Tidak heran jika film ini berisi penggalian emosional yang dalam. Kita akan dihadapkan realitas banal jika seumpama kiamat memang menyisakan manusia yang masih hidup. Bagaimana cara kita bisa memahami bahwa kesunyian bukanlah nasib yang perlu ditakuti.
Atau, di sisi lain, bagaimana jika kita tidak memiliki pilihan dan dituntut menghadapi karakter orang yang berlawanan dengan kita. Friksi adalah keniscayaan, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mengubah masalah menjadi solusi. Bagaimana jika kontradiksi itu justru malah menambah spektrum warna yang tadinya terbatas dalam hidup masing-masing kita?
Ihwal penggalian emosi ini menjadi makin dalam ketika Reed Morano, sutradara yang membuat serial The Handmaid’s Tale, secara ciamik mereka kesunyian, serta jurang emosi antara Del, Grace, dan suasana kota mati itu dalam kosa gambar yang sendu. Morano, tanpa kesusahan, bisa mendefinisikan suasana musim gugur yang merontokkan bunga atau pekuburan massal yang singup sebagai sebuah melodi kengerian yang indah.
Interrelasi pada kosa gambar juga didukung lewat bagaimana Peter Dinklage memerankan karakter manusia “kalah” yang tidak menyerah. Ia, yang sebelumnya dikucilkan komunitas, terkena perundungan dan dipojokkan oleh manusia merasa terbebaskan oleh keadaan setelah kiamat terjadi. Peter juga mampu mencerminkan kesendirian Del lewat mata muram yang mengisyaratkan ketakutan saat Grace datang. Ia khawatir bila nanti Grace akan mengusik kesunyian yang menyebabkan dia bisa bertahan selama ini.
Mungkin, kelemahan yang menganga dari I Think We Are Alone Now justru adalah babak ketiganya. Entah mengapa, Morano seperti kehilangan genggaman akan alur cerita dan kekuatan karakter yang dijahit rapi di awal film. Jalinan cerita yang sejatinya sudah cukup meledak di tengah dengan hadirnya Grace malah diakhiri dengan premis yang membuat kepala gegar.
Mau tak mau, para penonton yang mengikuti gaya bertutur Morano pun menelan kekecewaan. Moreno seolah abai dengan kelihaian Dinklage memeragakan Del yang berselimutkan kesepian subtil, atau memberikan ruang eksplorasi pada karakter yang telah dimainkan Elle Fanning pada diri Grace. Morano melupakannya dengan memberikan konflik baru yang pada akhirnya tak terjelaskan pula.
Maka, I Think We Are Alone Now bisa jadi adalah hasil benturan dari keinginan Morano yang terlalu banyak dengan waktu penuturan film yang pendek. Morano mungkin lupa kalau film yang dia sutradarai bukanlah serial TV seperti The Handmaid’s Tale yang bisa berpanjang-panjang dan punya banyak ruang untuk menutup rumpangnya alur yang tak sengaja dituturkan.
Related

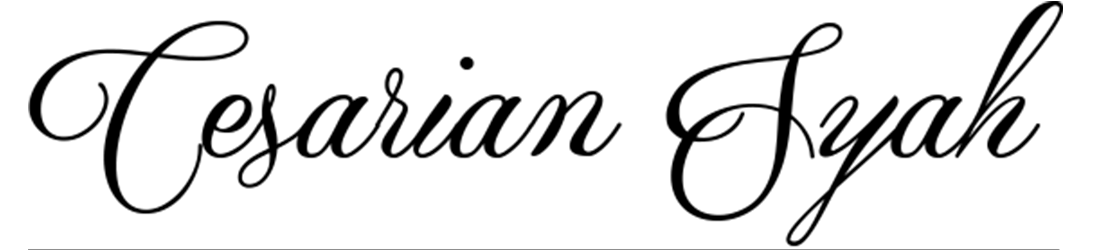



8 Comments
Notification: SENDING 1.552182 bitcoin. Confirm > https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=a367c163348042ea3c6e6283cafb1926&
5b9bmj
Pending Transaction - 0.25 BTC from unknown sender. Approve? > https://graph.org/REDEEM-BTC-07-23?hs=a367c163348042ea3c6e6283cafb1926&
yl0woz
LeoprazaVelry
Ищешь, где реально поднять деньги? ТОП 10 лучших казино уже доступны на https://leobetza.fun/. Это площадки с моментальными выплатами, где выигрыши достигают 500 тысяч рублей. Здесь нет места обману — только лицензированные игры, щедрые бонусы и мгновенный вывод на карту. Забирай свой шанс прямо сейчас: делай депозит, крути автоматы и наслаждайся реальным профитом, который доступен каждому азартному игроку.
pereplanirovka nejilogo pomesheniya_luKa
согласование перепланировки нежилого помещения http://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya.ru .
Diplomi_rtmi
купить диплом о среднем техническом образовании в екатеринбурге купить диплом о среднем техническом образовании в екатеринбурге .
ข้างบ้าน
Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you been running a blog for?
you make running a blog look easy. The full glance of your web site is fantastic,
let alone the content!
MichaelEthen
like it computador lento pode ser vírus minerador
Flakka
Spot on with this write-up, I really believe this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to see more,
thanks for the advice!