
Gula Kacang

“Sedoso Mas, niku angsal selangkung” (Sepuluh ribu Mas, dapat 25 buah)
“Nggih, Pak. Kulo tumbas sedoso ewu, nggih“
Bapak tersebut mengambil plastik bening dari bawah bakulnya. Ia mulai memasukkan satu per satu gula kacang ke dalamnya.
“Pak, saking jam pinten wonten menika ?”, Saya bertanya sejak pukul berapa ia datang di tempat ini.
“Sediluk Mas, kula tak ngitung sek ya”
Kegigihan melawan distraksi adalah penanda bahwa daya ingatnya mulai merapuh. Perlahan, ia menggumamkan deretan bilangan seraya menghitung gula kacang yang masuk ke dalam plastik. Saya memperhatikan jemarinya yang digurati pembuluh darah. Pembuluh yang mungkin cukup letih mengangkut waktu dan kegetiran usianya. Raut wajahnya biasa. Ia tidak memaksakan diri untuk menyunggingkan senyum palsu atas nama proyeksi keramahan.
Sang bapak juga membiarkan peluhnya menggantung di dahi dan pelipisnya. Tak terlihat saputangan atau handuk kecil untuk menyeka bulir peluh itu. Ia hanya mengenakan kopiah hitam. Kopiah hitam yang mungkin wujud upayanya untuk memayungi kepala dari panas matahari yang kian lama kian tajam.
“Sekedhap Mas. Siji, loro, telu….” Bapak itu menghitung ulang gula kacang yang tadi telah dimasukkan. Mungkin ia khawatir hitungannya salah dan mencederai perasaan saya. Atau mungkin saja ia lebih khawatir penyakit lupa memenangkan pertarungan atas kekuatan hapalannya.
“Niki, Mas“, Bapak itu memberikan sebungkus plastik gula kacang kepada saya.
“Niki artone nggih, Pak. Sedoso“, Selembar uang kertas bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II segera ia rengkuh dan ia masukkan ke saku kemejanya.
“Bapak saking pundi?“, saya mengambil sebuah gula kacang dan mengunyahnya. Beberapa kunyahan membuat rasa gurih dan manis seperti sedang bertengkar di lidah saya.
“Ungaran, Mas”
“Niki gulone ndamel piyambak nggih, Pak?”
“Nggih mas, ndamel teng griya“, Bapak tersebut baru saja mengiyakan bahwa penganannya ini ia buat sendiri di rumahnya.
“Matur nuwun, nggih Pak. pareng“. Saya pamit dari hadapan bapak tersebut. Istri dan anak saya sedang menanti di seberang jalan. Saya takut membuat mereka menanti terlampau lama.
Kala itu hari Minggu bertitimangsa 15 November 2015. Saya bersama istri dan anak saya sedang menikmati gelaran hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di sekitar Jalan Pahlawan kota Semarang. Dari jauh-jauh hari, saya dan istri saya sepakat untuk menggelari hari bebas kendaraan bermotor tiap minggu ini sebagai pameran paradoks.
Paradoks diawali dari penamaan hari bebas kendaraan bermotor. Satu ruas jalan memang sengaja dikosongkan dari kendaraan bermotor. Namun, pada pembatas jalan tampak ratusan kendaraan bermotor diparkirkan. Masyarakat datang dengan menaiki kendaraan bermotor. Agaknya, bebas kendaraan bermotor hanya ditafsir secara spasial saja dan bukan usaha mengurangi polusi. Sehingga, lanskap yang tersaji adalah benturan antara “bebas kendaraan bermotor” dan “parkir kendaraan bermotor” yang dibatasi sebuah garis penanda.
Sang bapak sendiri adalah simbol paradoks hari bebas kendaraan bermotor yang lain. Dengan usia yang makin menua, ia berjuang seorang diri memanggul dagangannya di tengah kerumunan mereka yang lebih muda. Ia hanya membawa baskom sebagai tempat penganannya dijual. Sementara di sekelilingnya, puluhan mobil, motor, dan stan-stan kecil berjejeran. Tidak ada hiasan atau penanda bahwa ia sedang berjualan. Tidak ada pula teriakan darinya untuk menjajakan dagangannya. Ia hanya duduk beralas aspal sembari menatap para muda-mudi itu baku pekik menjajakan dagangan mereka masing-masing. Mungkin pula ia sebenarnya ingin turut memekik. Namun, ia tercekat karena waktu telah merampas suaranya hingga parau saja yang tersisa.
Posisi sang bapak yang hanya duduk di aspal makin membuat ia sulit dinotifikasi. Dalam posisi duduk, ia hanya setinggi pinggang saya. Sedangkan para pejalan cenderung lebih mudah melihat para penjaja yang sedang berdiri. Maka, dagangan sang bapak pun sepi pembeli. Baskomnya hampir selalu tampak penuh.
Padahal, harga yang dipatok sang bapak untuk jajanan gula kacangnya cukup murah. Dua puluh lima buah gula kacang dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah. Harga tersebut tentu lebih murah daripada rata-rata harga penganan lain yang ditawarkan di sekitar lapak sang bapak.
Bapak itu masih diam ketika saya tinggalkan. Ia menatap dan mengerling sesekali. Entah berharap orang lain tertarik untuk mampir dan membeli dagangannya, atau mungkin takjub akan lautan manusia yang beberapa jam lalu tiada lalu tiba-tiba saja suah mengerumun. Saya gusar melihat perjuangannya. Perjuangannya yang tidak mengenal pensiun seperti para pegawai berhadapan dengan kenyataan bahwa tubuhnya merenta dan ia berhak untuk menggeluti tenang istirahat.
Di sudut-sudut lain, beberapa pengemis yang menengadahkan tangannya tertangkap mata saya. Mereka jauh lebih muda daripada bapak penjaja gula kacang. Tubuh mereka masih nampak kokoh. Para pengemis itu tak terlihat canggung mengiba untuk sesekali mendapatkan beberapa lembar uang kertas. Saya menjadi gusar dan melihat bapak penjaja gula kacang kembali. Ia masih belum beranjak dari tempatnya berjualan. Ia pun masih berhadapan dengan ketiadaan pembeli. Dagangannya masih banyak. Sementara pengemis-pengemis itu terlihat lebih mudah mendapatkan rejeki.
Saya jadi ingat dialog dengan istri saya dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang. Dia berkeinginan untuk sedapat mungkin membeli apapun yang dijaja oleh penjaja keliling. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah ikhtiar untuk membantu sesama manusia. Menurut istri saya, perjuangan manusia dalam menjaga api napas keluarganya adalah sebuah nilai yang luhur. Dengan membeli barang dagangan para penjaja, kita bisa turut membantu menjaga nyala api napas mereka beserta keluarga mereka.
Perjuangan untuk berdagang, menurut istri saya, lebih mulia daripada mereka yang menengadahkan tangan padahal tubuh masih kokoh. Bapak penjaja gula kacang menumbukkan ingatan saya akan dialog tersebut. Ia masih mewujudkan perjuangan walau tubuhnya sudah tidak kokoh. Sejumput harapan terus ia jaga. Sejumput harapan yang saya belum berhasil menerkanya.
Dua bulan berlalu Saya kembali hadir pada gelaran hari bebas kendaraan bermotor. Manusia tampak riuh memenuhi bilangan Jalan Pahlawan hingga Taman Menteri Supeno. Penjaja makanan dan minuman bertambah banyak. Paradoks kembali hadir lewat padatnya ruas jalan yang tidak boleh dimasuki kendaraan bermotor oleh ratusan pasang kaki. Mereka yang hilir mudik menyebabkan ekses berupa sampah. Jika hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk mengurai polusi, maka gelaran itu hanya mampu mengurai polusi udara. Namun polusi berupa sampah malah terhambur di sana-sini.
Saya sedang melangkah pulang ketika berpapasan kembali dengan bapak penjual gula kacang. Ia berada di tempat yang sama saat pertama kali saya menemuinya, duduk termangu sembari menggelar penganan yang ia jual. Bahkan, ia mengenakan kemeja batik dan jaket yang sama. Matanya sayu diterpa terik matahari. Mungkin, ia makin letih berebut napas dengan pengunjung yang riuh berlalu.
Kali ini, istri saya yang menemuinya. Istri saya membeli satu plastik penuh dengan gula kacang. Harganya masih sama, sepuluh ribu rupiah. Dari jauh, raut mukanya masih terlihat sama seperti dahulu. Ia belum mendapatkan banyak pelanggan terlihat dari baskomnya yang penuh padahal gelaran hari bebas kendaraan bermotor akan segera berakhir. Istri saya melihat saya sembari menunjukkan rasa iba.
Sekitar sebulan sebelumnya, istri saya turut membantu menyebarkan foto sang bapak di Facebook disertai ajakan untuk turut membeli penganannya. Foto tersebut cukup viral dengan ribuan “share” dan “like“.
Saya memahami raut iba istri saya. Puluhan ribu “like” tidak berimbas terlalu banyak rupanya. Sang bapak masih duduk lesehan di aspal, berbincang dengan minimnya pelanggan. Ia masih menggeluti perjuangan menjaja hingga gula kacang habis tak tersisa.
Satu plastik gula kacang digenggam istri saya. Saya mengambil sebuah gula kacang dan menggigitnya. Rasa gurih dan manis masih bertengkar hebat di mulut. Sang bapak jelas menjaga kualitas jajanannya. Sembari mengunyah, kami pun melangkah pergi sambil berbisik dalam hati: “Andai saja, atau semoga saja, gurih dan manis selalu menjadi rasa yang dicecap sang bapak sepanjang hidupnya”
Di perjalanan pulang, matahari tiba-tiba pergi dan awan mendung berarak turun. Tetes demi tetes hujan mengguyur badan jalan, kendaraan, hingga pepohonan. Mata saya berpendar membayangkan sang bapak sambil berharap: semoga engkau berteduh di tempat pengananmu kelak dijaja hingga habis tak tersisa.
Related
You May Also Like
Rangkaian Keajaiban di Semesta Fantasi Ziggy
04/04/2017
Headshot dan Kelelahan-Kelelahannya
21/12/2016
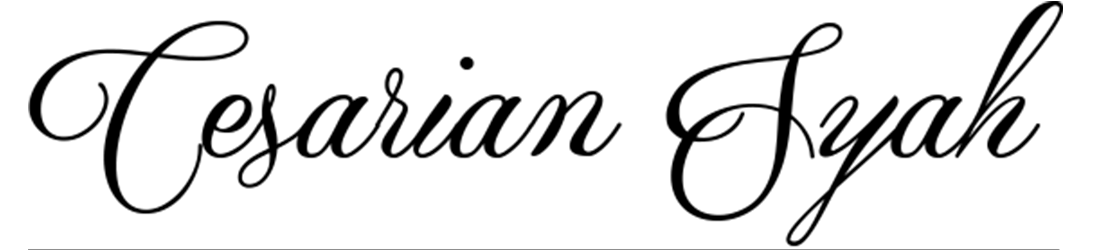


776 Comments
Febriyan
Perjuangan bapak ini luar biasa. Tfs.
Meidiawan Cesarian Syah
Iya Mas. Bapak ini mungkin hanya sebuah contoh dari banyaknya pejuang-pejuang serupa di tempat lain. Semoga mereka selalu diberi keberkahan
Dani
Mengaminkan doanya Mas. Teringat Bapak saya setelah baca postingan ini.