Yang Bukan Jazz di Festival Java Jazz

Sore itu, si lelaki muda memilih setelan jas dibandingkan kemeja batik. Padahal, rekan-rekannya bersetia dengan kostum manggung seperti biasa. Mungkin karena ini adalah festival jazz terbesar di belahan bumi selatan, ia ingin memberi kesan berbeda, pikir saya. Tapi, selain jas, dandanannya sama belaka. Ia masih meminyaki rambut dan menyisirnya ke belakang. Juga matanya yang tampak tak bisa dibuka lebar-lebar itu. Ketika jemarinya mulai menggasak senar-senar gitar dan membuka larik suara, saya tahu benar: ia juga tidak mengubah aransemen lagu-lagu mereka menjadi jazz. Mereka tetap mengocok telinga lewat musik rock.

Lelaki itu, Iga Massardi. Bersama bandnya, Barasuara, menjadi salah satu pengisi Java Jazz Festival yang dihelat 3 hingga 5 Maret 2017 lalu. Barangkali sebuah festival jazz menampilkan musisi rock terdengar aneh. Namun, Barasuara nyatanya bukan satu-satunya. Sebut saja Andre Harihandoyo & Sonic People, Fourtwnty, Soundwave, Gugun Blues Shelter, Hivi!, Armand Maulana, G-Pluck, Teddy Adhitnya, hingga The Overtunes. Belum lagi nama-nama besar seperti Afgan, Ne-yo, hingga Naughty by Nature yang masing-masing lekat dengan genre pop, R&B, dan hiphop.

Sejak kali pertama diselenggarakan pada 2005, Java Jazz Festival memang tidak hanya menampilkan musisi jazz. Bahkan, tidak sekali dua musisi non-jazz menjadi bintang utama di Special Show. Tahun lalu, misalnya, ada Sting. Pada 2015, Christina Perry dan Jessie J. Pada 2013, giliran Joss Stone dan Craig David. Dan tahun ini, ada Ne-yo dan Naughty by Nature: dua nama yang tadi sudah saya sebut.

Jika jazz boleh diibaratkan sebuah agama, Java Jazz Festival sudah bisa dicap kafir karena menghadirkan begitu banyak musisi non-jazz walaupun nama festivalnya sendiri menggotong kata jazz. Jika bukan kafir, minimal bid’ah – tetap saja rentan dibakar bersama gunggungan penista agama lainnya. Untungnya, para pembela jazz puritan tidak ikut-ikut membuat ormas menggunakan nama yang berawalan “front”.
Tapi, kita harus mampu memahami mengapa penyelenggara Java Jazz Festival sengaja melebarkan spektrum musik yang mereka sajikan. Jazz bukanlah musik yang punya denyut di seantero negeri. Piuh-piuhnya yang unik dan suara detaknya yang tidak ritmis sulit dinikmati. Belum lagi asosiasi yang melekat dalam tempurung kepala mayoritas penduduk negeri ini: jazz adalah musik para borjuis dan sebuah perlambang gaya hidup. Jazz semakin berada di atas menara babel yang tak teraih. Penikmatnya terbatas. Ironis, memang, jika dibandingkan dengan asbab lahirnya jazz di kampung halamannya. Dan untuk meruntuhkan ironi itu, rata-rata festival jazz memang tidak boleh tertutup. Mereka harus berani untuk tidak melulu bicara tentang jazz, tetapi lebih ke bagaimana jazz dapat didiangi lebih banyak orang.
Sepanjang acara, saya maklum belaka melihat para musisi berlomba menghasilkan gigil pada kulit dan merdu pada telinga, terlepas mereka betul-betul memainkan jazz secara kaffah atau tidak. Musik jenis itu pula yang justru saya nikmati dalam-dalam: Barasuara yang memainkan rock.
Lewat formasi lengkapnya, Barasuara tak ragu mempercepat darah di pembuluh lewat lagu-lagu seperti “Sendu Melagu”, “Tarintih”, “Bahas Bahasa”, dan “Api & Lentera”. Komposisi ini menjadi lebih semarak diiringi horn section milik Ron King. Mengetahui mereka hanya sempat berlatih bersama selama satu jam, saya kira penampilan mereka sangat baik. Jika punya lebih banyak waktu, pasti kolaborasi lintas genre ini bakal lebih padu.

Barasuara adalah musisi pertama yang saya saksikan di hari ketiga festival tersebut. Hari sebelumnya, Sabtu, saya mencicipi musik-musik non-jazz yang juga tak kalah bagus: Yamaha Music Project. Grup ini berisi Tulus, Armand Maulana, Yura Yunita, Saykoji, dan Glenn Fredly. Saya pilih mereka sebagai hidangan pembuka Java Jazz tahun ini, sebelum menikmati eksotisme penampilan Afgan. Keduanya sama-sama memperlihatkan kualitas prima sebagai bintang. Mereka ciamik dalam bermacam hal. Jika Yamaha Music Project membagi rata kesempatan menjajal panggung D2 pada kelima artisnya, maka Afgan, dengan jajaran band yang sangat lengkap ditambah saksofon dari Kirk Whallum, membuat pemudi di Hall B3/C3 tidak ragu berteriak manja nan menggemaskan. Terlebih saat ia menafsir ulang lagu Bruno Mars, “Versace on The Floor”.

Setelah menyesapi Barasuara, saya bergegas menuju ke panggung yang menampilkan Glenn Fredly. Berbeda ketika tampil bersama Yamaha Music Project, Glenn justru lebih memikat kala tampil solo. Lagu demi lagu bernuansa pop berhasil ia urai dengan indah dan menyenangkan. Sayangnya, saya kira, Glenn harus mengurangi kegemarannya berbual-bual terlalu lama di sela lagu. Selain membosankan, saya takut penonton tidak bisa membedakan antara Java Jazz dan kontes dangdut di sebuah stasiun televisi.

Lepas dari Glenn, saya menyempatkan untuk mendengarkan sayatan apik dari dua bidadari secara berurutan: Monita Tahalea dan Eva Celia. Mereka yang sama-sama tumbuh dari tempaan Indra Lesmana ini, sungguh menghibur pancaindra dengan ciri khasnya masing-masing. Baik Monita maupun Eva Celia punya kemiripan tekstur suara: sama-sama tipis dan terkesan effortless. Keduanya membawakan lagu-lagu dari album terbaru masing-masing, Dandelion dan And So It Begins. Menurut saya, kedua album ini layak masuk jajaran album jazz lokal terbaik tahun lalu.


Eva Celia adalah artis jazz terakhir yang saya saksikan. Setelahnya, saya memutuskan kembali ke ranah non-jazz. Ne-Yo sedang tampil di panggung utama, Hall B3/C3. Saya merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Dari gestur lempar kaos, hingga sing-a-long, tak ketinggalan penonton mengangkat tangan bersama. Nuansa festival jazz lenyap, berganti suasana konser RnB. Untunglah, begitu keluar, saya mendengar sayup-sayup Tiyo Alibasjah feat Karim Suweileh. Mereka membuat saya kembali merasakan sebuah festival jazz.

Rangkaian Java Jazz itu ditutup dengan penampilan eksentrik dari musisi dengan penggemar paling banyak di Indonesia: Virgiawan Listanto alias Iwan Fals. Iwan, yang jelas-jelas tidak ada jazz-jazz-nya itu, masih setia menyuarakan kritik yang melampaui usianya. Dengan sisa rambut yang telah memutih dan teriakan yang tak lagi lantang, “Bongkar” tetap berhasil menarik saya ke suasana layaknya sebuah demonstrasi massa. Lalu mendadak romantis ketika “Izinkan Aku Menyayangimu” dilantunkan. Namun, saya tersentak kala teriakan-teriakan Iwan menyebut “Hio” berulang-ulang. Belum lagi ketika Maurice Brown dan Kirk Whallum mengiringinya sambil berdansa. Epic sekaligus apik.


Meski tampak banyak, 14 panggung yang disiapkan pada Java Jazz Festival tahun ini hanya memberikan jatah sekitar 40% untuk musisi non Jazz. Sisanya tetap diprioritaskan untuk musisi jazz. Bandingkan, misalnya, dengan festival tahun lalu yang memberi separuh jatahnya untuk musisi non jazz. Java Jazz tahun ini lebih membuka ruang untuk tafsiran-tafsiran jazz baru, terlebih dari musisi jazz lokal.
Sayangnya, jazz lokal dinilai masih jalan di tempat. Musisi-musisi baru tidak bisa langsung berjajar dengan musisi jazz kawakan. Meski diberi panggung lebih banyak dari tahun lalu, keterdengaran mereka tidak terlampau masif. Belum lagi konsep tahun ini meniadakan special show. Popularitas jadi lebih banyak berbicara. Walau demikian, usaha festival ini mengenalkan jazz tetap layak diacungi jempol. Menurut saya, segregasi genre memang bukan untuk saling meniadakan. Justru spektrum ini bisa menjadi pengikat sekaligus pengingat, bahwa Indonesia sendiri tak jauh beda dengan Java Jazz: meski berbeda-beda, kita menghadapi dunia dengan luka yang sama.
Related
You May Also Like

Pesan-Pesan dari Poso
27/12/2016
Lee Chong Wei, Legenda!
14/06/2019
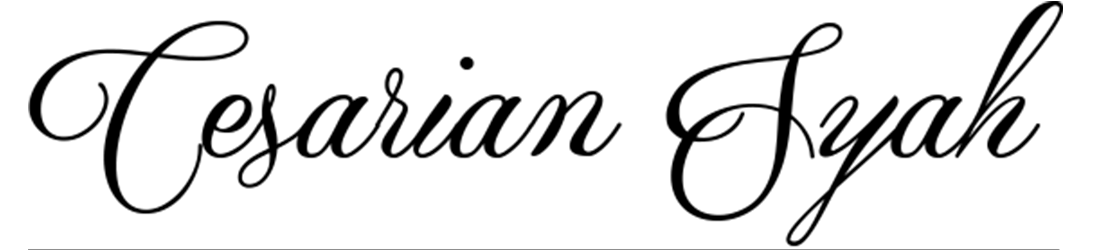
143 Comments
Artha Amalia
Suka jazz ya? Kalau mau beli kaset dan CD jazz bisa via priceza.co.id loh. Harga terjangkau dan ori. Kalau Java Jazz sendiri saya pernah dengar diselenggarakan di Bromo. Ada Andien waktu itu. Lupa tahun berapa, hehe
Meidiawan Cesarian Syah
Iyaaa suka jazzz heheheee. Makasih ya rekomendasinya. Nanti kalau ada yang menarik, saya berkunjung deh
Freddy Gunawan
I love Glenn so much! Nice Story Bro!
Meidiawan Cesarian Syah
You’re welcome bro