
Kerja

Sedikitnya lima hari dalam seminggu, sinar matahari terbit akan saya tentang demi berangkat menuju kantor. Debu dan asap juga menjadi karib mengiringi perjalanan yang biasanya memakan waktu 15 menit itu. Tempat yang saya tuju adalah sebuah gedung megah di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di sanalah, sembilan jam waktu saya amblas untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan bekerja.
Pekerjaan adalah sebuah identitas. Dalam Kartu Tanda Penduduk, jenis pekerjaan tertulis tepat di bawah identitas status perkawinan. Orang-orang sering bertanya “kerja di mana?” kepada relasi-relasi baru mereka. Pekerjaan juga menjadi salah satu identitas awal yang ingin kita ketahui tentang lawan bicara kita. Kesemua ini membuat pekerjaan, mau tidak mau, menjadi sesuatu yang penting untuk dimiliki.
Sebagai sebuah identitas, pelbagai asumsi tak pelak hadir dalam memandang pekerjaan. Misalnya, pekerjaan sebagai pegawai yang dalam konsensus masyarakat tradisional lebih terhormat dibandingkan mereka yang bekerja tidak tetap, atau sektor formal yang terlihat lebih menawan daripada sektor informal. Anggapan lain menilai sektor pegawai terbagi-bagi menjadi krah putih dan krah biru. Krah biru yang terasosiasi dengan para pekerja kasar dan krah putih yang berasosiasi dengan para pekerja kantoran.
Tapi, setujukah kita terhadap penyederhanaan dan generalisasi semacam itu? JIka tidak, bagaimana sebetulnya kita harus memandang pekerjaan? Apakah hakikat pekerjaan sesungguhnya?
Ketika abad masehi belum bermula, filosof Yunani menganggap pekerjaan adalah sesuatu yang rendah. Masyarakat kota (polis) sangat menghormati waktu luang sehingga mereka yang tidak perlu bekerja keras dianggap sebagai warga negara dalam arti sebenarnya. Kala itu, Aristoteles mengamini risalah Plato yang berpendapat bahwa aktivitas manusia paling mulia adalah pengembangan diri seperti kegiatan ilmiah (theoria) dan sosial politis (praxis). Kegiatan bekerja (poesis) tidak bernilai apa-apa karena dianggap hanya aktivitas membuat bentuk secara fisik saja.
Anggapan ini berubah ketika abad modernisasi datang. Mula-mula John Locke menyatakan pendapat bahwa pekerjaan menciptakan nilai ekonomis. Lalu Adam Smith dan David Ricardo mengambil alih ide Locke dan menyebut pekerjaan adalah sumber dari hak milik pribadi.
Di tempat lain, para filosof Jerman mengambil kajian berbeda mengenai hubungan manusia dengan pekerjaan. Pekerjaan, menurut mereka, membentuk kepribadian manusia dan sifat historisnya. Hegel, misalnya, mengemukakan bahwa pekerjaan adalah cara manusia “menciptakan diri”. Marx pun mengamini Hegel dan menambahkan perihal “penciptaan diri” itu berkelindan dengan identitas individual, sosial, dan historis.
Lebih lanjut, dalam masyarakat modern Jerman sendiri terdapat istilah Arbeitsgesellschaft atau Working Society. Mengutip Haeffner, tatanan working society percaya bahwa pembagian nilai-nilai sosial, kesempatan-kesempatan kehidupan, wibawa sosial serta perasaan harga diri individual untuk sebagian besar diatur melalui pekerjaan yang dibayar.
Pendapat dari para filosof Jerman inilah yang saya kira teraplikasikan tanpa sadar dalam konstelasi umum masyarakat kita. Kita lebih mudah memberikan kepercayaan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan bonafide daripada yang tidak. Sebaliknya, pekerjaan yang bonafide tidak hanya menjanjikan kemapanan finansial bagi orang tersebut, tapi juga harkat dan wibawa yang tinggi di mata masyarakat sekitar. Pekerjaan, pendeknya, menjadi jembatan untuk menciptakan kemuliaan diri.
Tak heran jika jenis pekerjaan yang bonafide menyedot banyak sekali peminat. Para peminat itu ingin mereguk kemapanan finansial sekaligus menaiki tangga sosial, dua pulau yang bisa dilampaui dalam sekali merengkuh dayung. Dengan demikian, secara sadar maupun tidak, mereka menjadi pelaku yang bisa menjembatani konsep pekerjaan dari Locke maupun Hegel.
Tapi, apa benar kita hanya mengincar status sosial dan finansial saja dalam bekerja? Pertanyaan ini patut diajukan ke masing-masing kita secara terus menerus. Kita tidak bisa begitu saja abai terhadap pendapat Marx soal pekerjaan yang “menciptakan” kita. Betapa mengerikannya jika setiap orang mencari pekerjaan hanya untuk status sosial dan finansial semata. Pekerjaan bisa berubah fungsi dari jembatan menjadi tujuan hidup.
Zinn, seorang antropolog Jerman, menyebut pekerjaan memiliki tiga fungsi antropologis yaitu reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. Fungsi pertama dan kedua sudah terepresentasikan dan cukup akrab dimaknai oleh masyarakat Indonesia. Fungsi antropologis ketiga, pengembangan diri, baru dilirik belakangan setelah fungsi pertama dan kedua terpenuhi.
Padahal, pengembangan diri, sesuai pendapat Aristoteles, adalah sikap yang mengantar manusia mencapai kemuliaan. Status sosial dan finansial memang bisa saja masih terengkuh, namun kedua fungsi itu menjadi semu belaka. Absennya fungsi pengembangan diri juga membuat pekerjaan tak lebih dari ritual tanpa arti. Pekerjaan, agaknya, bisa membuat hidup termekanisasi. Manusia menjadi mesin-mesin yang akan teronggok begitu saja setelah mereka tidak terpakai.
Pekerjaan adalah salah satu pembangun identitas utuh manusia. Ia adalah atribut, tapi tidak melulu mewakili identitas utuh. Manusia bukan sarden kaleng yang bisa diberi merk sesederhana itu. Pekerjaan, menjadi identitas berarti ketika di dalamnya terkandung aktivitas pengembangan diri dan aktivitas sosial, bukan hanya alat mencapai kewibawaan dan kekayaan. Sehingga kita juga harus sedikit memunggungi Marx dan mulai menjabat Aristoteles. Pekerjaan tidak menciptakan kita. Ia hanya mencipta bagian dari identitas kita.
Related
You May Also Like

Sehari Sebelum Lebaran Tiba
06/06/2019Fast Fashion adalah Kegelapan Kita
22/06/2017
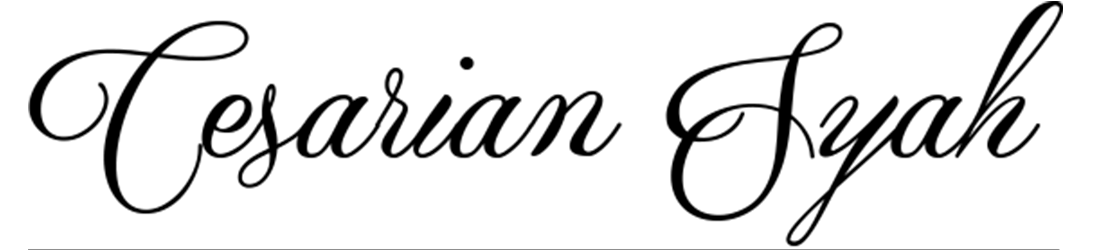


5 Comments
Ikrom
Pekerjaan, menjadi identitas berarti ketika di dalamnya terkandung aktivitas pengembangan diri dan aktivitas sosial, bukan hanya alat mencapai kewibawaan dan kekayaan.
—
sepakat, bekerja itu bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya
menjadi manusia yang berguna bagi sesama
Meidiawan Cesarian Syah
iyes kak…aamiin. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Menjadi manusia berguna bagi sesama.
Hastira
ketka kita menicntai pekerjaan dg hati, semua akan jelas adanya, kita akan berkembang dan kreatif dan bisa menumbhkan semangat baru untuk selalu maju,tapi org seperti itu serignya malah dibenci krn bikin iri org lain yang gak suka dg kemajuan
Meidiawan Cesarian Syah
siap kak, betul sekali….Yang penting diri sendiri kudu bakoh dan cinta
Pingback: