
Sehari Sebelum Lebaran Tiba
Mungkin memang benar Jakarta adalah rumah bagi keangkuhan. Ada kalanya, kota ini merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka tidak perlu, atau tidak merasa katakanlah butuh, bantuan orang lain. Sehingga ada rasa risih bagi sebagian penduduknya ketika tahu beberapa juta orang saban harinya datang hanya untuk mengais nasib di sana lalu kembali pada sore harinya. Risih yang masih tetap terasa di kerongkongan meskipun mereka datang dari daerah-daerah yang letaknya mepet Jakarta. Kumpulan tetangga sendiri.
Mereka lupa, bahwa banyak dari mereka yang mencecap risih itu asalnya pendatang juga. Entah karena pekerjaan atau lain hal, mereka jadi menetap dan mengantungi kartu yang menandakan mereka adalah penghuni tetap Jakarta. Jakarta, sebuah imaji yang mereka bangun di kepala mereka, tak lebih dari jalin jemalin rasa yang dihidangkan oleh rupa-rupa manusia yang mengantri di Tanah Abang, bekerja di Sudirman, menguli cetak di Bungur, atau para pelaju dari Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, atau Bogor. Jakarta adalah kuali tempat luruhnya budaya-budaya. Tempat bergaulnya nuansa-nuansa.
Pada satu atau lain titik dalam setahun, akan ada saat-saat ruang Jakarta mencelos karena para penghuninya kembali ke asal. Saat inilah kita bisa melihat, atau kalau boleh, menyaring mana-mana saja yang mungkin bisa disebut Jakarta totok: lahir dan hinggap di sini lebih dari dua atau tiga generasi. Salah satu periode itu adalah musim lebaran.
Ketika musim lebaran tiba, saya merasa Jakarta seperti mayat kehilangan nyawa. Jalanan yang dibangun bertumpuk-tumpuk, kadang saling menyilang dan menindih, hanya dilalui oleh segelintir kendaraan. Saya bisa berlarian menyeberangi flyover Slipi, yang kemarin menjadi tempat pesta perkelahian api dan air yang saling bekerja, tanpa melalui jembatan penyeberangan sambil melepaskan kekhawatiran untuk tertabrak. Saya juga bisa berjalan dengan earphone di telinga dengan santai menyusuri ruas-ruas jalan yang biasanya dijejali wajah-wajah yang kuyu, lelah, sambil menanti kapan tanggal gajian berikutnya.
Jakarta, yang sepi, juga membuat saya lebih lapang memandang. Saya menyaksikan beberapa orang yang masih kukuh menjajakan barang dan jasa yang mereka miliki. Para petarung tangguh, dalam batin saya. Ada pemuda tanggung yang sepertinya baru lulus Sekolah Menengah Atas sedang menjajakan aneka tutup kepala, juga tukang cukur yang cukup kerepotan menghantam rambut mereka yang tentu menganggap hari raya adalah salah satu waktu terbaik memajang kerupawanan
Tentu, yang tidak bisa dilupakan adalah mereka yang harus terus bekerja meski warna merah menyala-nyala pada tanggal di kalender. Entah apa rasanya datang, duduk, lalu menanti kekosongan demi kekosongan berlalu di hadapan mereka. Sementara, lewat gawai yang mereka gunakan untuk melalui kebosanan, puluhan atau ratusan orang lain sedang mengunggah momen kepulangan mereka lewat gambar-gambar. Mereka pun hanya bisa menatapnya. Kepulangan yang sebenarnya mereka rindukan juga, tetapi terbatasi oleh garis nasib yang membelah harapan itu dengan kenyataan yang harus mereka arungi.
Saya menangkap harap pada mata mereka yang layu diterpa angin kering. Beberapa penjaga halte bus TransJakarta yang saya naiki entah sudah dalam berapa waktu terus menerus berada di luar kotaknya. Mereka pun sesekali memandangi lorong halte yang jauh dari hingar bingar. Dua atau tiga kali saya mencoba melempar senyum terbaik, tetapi mereka tetap bergeming. Pandangan ke layar gawainya begitu memaku. Saya mencoba memahami keramaian yang direnggut dari keseharian mereka. Mungkin, bagi mereka, kesepian lebih nyeri dibandingkan pejal manusia yang mereka saksikan tiap hari.
“bagi mereka,
kesepian lebih nyeri
dibandingkan pejal manusia
yang mereka saksikan tiap hari”
meidiawancs
Keramaian bukannya benar-benar hilang, ia hanya berpindah. Stasiun MRT Bundaran HI masih dipenuhi para Jakartans yang berwisata. Baik bersama keluarga atau seorang diri. Entah sekadar menuju ke arah Lebak Bulus lalu kembali lagi atau berjalan-jalan di sekitaran trotoar Bundaran HI yang sore itu sejuk dan sepi. Saya memilih yang terakhir. Bangku di trotoar yang nelangsa menjadi saksi bagaimana saya mengalahkan seratus lima puluhan halaman buku “Dongeng dari Negeri Bola” milik Dalipin.
Entah mengapa, saya merasa ramainya Jakarta sore itu telah rontok. Bukan jumlahnya, melainkan berkurangnya mata yang curiga atau ketergesaan yang buru memburu di jalan. Yang tinggal hanyalah pejalan-pejalan yang santai dengan wajah-wajah sumringah tanpa ketakutan akan cicilan rumah atau tenggat pekerjaan yang mencekat leher masing-masing. Jakarta menjadi tempat terbaik untuk bercengkrama dengan kesayangan.
Hanya beberapa ruas-ruas jalan yang masih terlihat sibuk. Jalan Sabang, salah satunya. Sepertinya, libur tidak melulu menjadi pilihan utama bagi para pedagang ini. Hari terakhir puasa mereka manfaatkan untuk menggelar dagangan sebanyak-banyaknya. Mereka mungkin tahu, keterbatasan pilihan warga Jakarta kelak membawa mereka ke sini pula: salah satu tempat terbaik untuk menghabiskan uang bagi para penggila makanan.
Namun, beberapa toko sudah tutup dan menggulung dagangannya rapat-rapat. Kertas bertuliskan “Buka lagi 10 Juni. Mohon Maaf Lahir Batin,” ada di depan pintu yang digerendel. Saya hanya bisa memandang penuh kegetiran. Sehari sebelum lebaran tiba dan Jakarta mengajarkan kalau kepulangan bisa bermakna banyak. Antara keridlaan untuk menerima diri yang sesungguhnya memiliki asal dan mengosongkan kecemasan yang berpendar di dalam kepala setiap hari. Jakarta, yang angkuh itu, juga butuh kepulangan agar ia bisa beristirahat dari memangku lelah semua pahit manis nasib penduduknya.
Kepulangan mungkin adalah keniscayaan. Sesuatu yang bisa meruntuhkan angkuh, meredakan riuh dalam penat-penat yang kian bergemuruh. Tetapi, tidak semua orang selalu bisa memilih untuk pulang. Walaupun demikian, saya percaya bahwa di tiap semoga, ada amin yang terlontar untuk setiap keinginan menemui asal, menawarkan tawa, dan menghilangkan semua dahaga pertemuan dengan orang-orang kesayangan kita. Selamat pulang bagi yang pulang. Selamat melawan kebosanan bagi mereka yang tetap berdagang.

antara pulang dan dagang
pulang hanyalah milik mereka yang melaksanakan pergi
Related

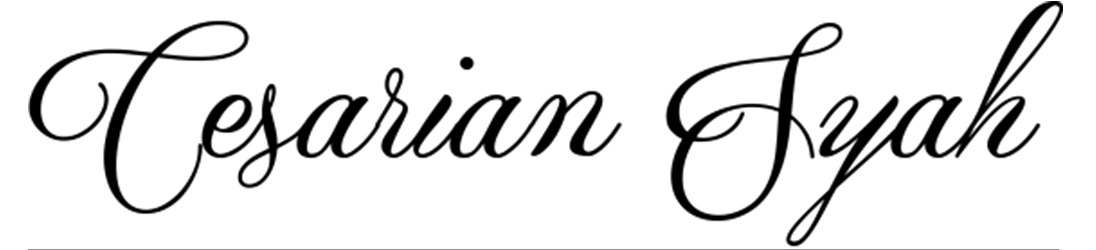






















5,300 Comments
Ubay
Keren sekali Jakarta dengan segala isinya terlihat sendiri. Betul juga, pulang hanyalah milik mereka yang melaksanakan pergi. Itu Jakarta. Narasi dan fotonya mantap mas.
Salam
http://www.kidalnarsis.com
Anonymous
Salam. Bagi yang pernah tinggal di Jakarta, membaca Jakarta adalah kesenangan tersendiri. Hehe, matur nuwun.
https://nggedabrusrek.wordpress.com/2018/12/12/kucintai-kota-ini/
Ditta
Tulisannya bagus. Bikin tertarik untuk baca cerita lainnya, gambar yang diambil juga bagus saya suka warna tone nya jadi betah liat gambarnya lama-lama