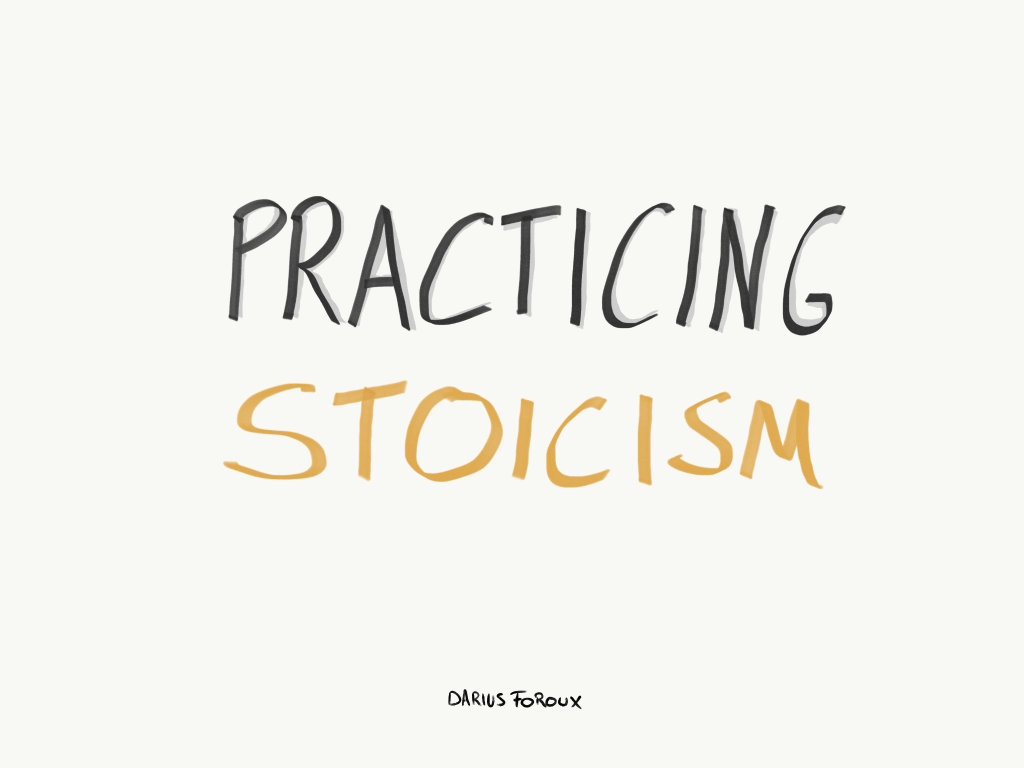
Berani Stoic itu Baik
Kau mungkin lelah dengan hidupmu. Kepalamu penat dan membuat semua yang kau lakukan terasa berat. Kau pun lelah menerka-nerka masa depan, atau mengapa kau bisa merasa demikian. Bisa jadi alasannya karena kau sadar (atau malah tidak?) bahwa ada sekitar 7,7 Miliar manusia yang menghuni bumi yang kian renta ini. Mereka memenuhi dunia tempatmu hidup dengan raga, pikiran, dan kata-kata.
Kepalamu menjadi semakin berat. Dunia membebankan ekspektasinya kepadamu lewat siapa saja. Mereka tak peduli dan memperhitungkan soal rasa dan asa yang kau punya. Mereka lepas dari tanggung jawab ihwal tawa dan duka yang kau derita. Dunia, beserta isinya, tak lebih dari jeruji yang menjadi penjara bagi raga, juga jiwa
Resultan dari semua himpitan itu membuatmu tertekan sedemikian hingga. Di tengah kejengahan dengan realita, kau mencari oase yang semurni-murninya. Bukan saja ingin menghirup dan menenggak sedikit airnya, kau juga ingin tinggal di sana. Kau ingin hidup berjalan dengan nyaman seperti genangan air di danau: tenang, diam, dan tak beriak. Kau ingin, sedikit saja, tahu bahwa gegap gempita kegelisahan tidak berpengaruh apa-apa kepada yang kau sebut semesta.
Perasaan-perasaan semacam itu sudah seperti daftar wajib yang dicentang dalam problem kehidupan kita. Di titik ini, tak sedikit orang yang mencari panacea, entah yang betul-betul mengobati atau hanya memberi efek placebo semata. Dan, di belantara solusi itu, Stoisisme menjadi salah satu cara yang bisa dipraktekkan untuk mengendurkan depresi serta tekanan dalam kehidupan.
Stoisisme pertama kali lahir pada 300 SM dan diajarkan oleh para filsuf Stoic awal di bawah teras terbuka di Yunani. Selanjutnya, stoisisme diamalkan betul oleh para raja dari kekaisaran Roma, termasuk Marcus Aurelius. Bersama Seneca dan Epictetus, gagasan Stoic yang diamalkan Marcus Aurelius bertahan sampai sekarang.
Yang membuat Stoisisme begitu relevan dengan masa kini adalah bagaimana ia berfokus dalam memegang teguh prinsip bahwa kunci dari kehidupan yang bahagia sentosa adalah dengan mengolah sikap mental yang oleh para Stoic diejawantahkan dengan kata “kebajikan” dan “bersikap rasional”. Kedua sikap itu dielaborasi menjadi, minimal, tiga butir prinsip yang mudah dicerna.
Kontrol Apa yang Kita Pikirkan
Epictetus menelurkan dua prinsip bagi para Stoic. Yang pertama adalah ada beberapa hal yang berada dalam kendali kita, sementara beberapa yang lain tidak. Sebagian besar ketidakbahagiaan kita disebabkan oleh pikiran bahwa kita dapat mengendalikan hal-hal yang, pada kenyataannya, kita tidak bisa.
Lalu, apa yang bisa kita kendalikan? Epictetus berpendapat bahwa hal yang bisa kita kendalikan sangatlah sedikit. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan atau dilakukan orang di sekitar kita. Bahkan, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh sendiri, yang tiba-tiba sakit dan pada akhirnya mati tanpa peduli. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana persepsi kita tentang hal-hal tadi.
Ini kemudian membopong kita pada prinsip dasar kedua dari Epictetus, soal bagaimana kita berpikir tentang berbagai hal tadi. Jika kita berpikir bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi, maka kita mungkin menjadi sedih, kecewa, atau marah. Pun jika kita menduga bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita mungkin akan merasa takut. Semua emosi ini adalah produk dari asumsi dan dugaan kita.
Padahal, semua kejadian tadi sebenarnya netral belaka. Apa yang mungkin tampak mengerikan bagi kita bisa jadi cuma remeh-temeh bagi orang lain, atau bahkan disambut bak gegap gempita oleh mereka yang lain. Respon emosional lah yang menggerus kewarasan kita.
Stoic yang baik adalah mereka yang memiliki kendali penuh atas emosi mereka. Mereka sadar bahwa hal-hal yang terjadi tidak ada yang mutlak baik atau buruk. Ini adalah soal bagaimana kita mampu untuk memandangnya. Paradoks Stoisisme, seperti yang dirumuskan Epictetus, adalah bahwa kita hampir tidak memiliki kendali atas apa pun, namun pada saat yang sama kita berpotensi mengontrol penuh sepenuhnya atas kebahagiaan kita.

Latih Pikiran Kita
Para Stoic bukanlah mereka yang lempeng-lempeng saja seperti tidak punya masalah. Justru sebaliknya, mereka secara utuh mengakui bahwa hidup kadang-kadang bisa menjadi sulit.
Bakan Seneca sendiri mencecap pengalaman yang luar biasa pahit: dia diasingkan, mendapati banyak kematian, hingga akhirnya dipaksa bunuh diri oleh Nero. Dia juga tahu bahwa, “tak semudah itu, Ferguso!” untuk mengatakan, “Saya tidak akan membiarkan hal-hal eksternal ini mengganggu saya”. Sebisa mungkin ia melakukan pelbagai hal lain agar tidak terganggu oleh pikirannya sendiri.
Para Stoic pun mengembangkan serangkaian latihan praktis untuk melatih orang agar mampu mengimplementasikan ide-ide Stoisisme ke dalam kehidupan sehari-hari. Seneca merekomendasikan kita untuk mencatat hal-hal apa yang membuat kita jengkel atau marah setiap harinya. Dengan mencatat kesalahannya, ia berkeingunan melakukan perbaikan pada hari berikutnya.
Marcus Aurelius punya strategi lain. Setiap pagi, ia mengingatkan diri sendiri kalau ia mungkin bakal menghadapi banyak orang yang marah, stres, tidak sabar, dan tidak tahu berterima kasih sepanjang hari. Dengan cara ini, ia akan cenderung sinis pada siapapun. Namun, di sisi lain, ia juga menaruh simpati terhadap kenyataan bahwa tidak ada dari orang-orang tadi yang melakukan segala hal menyebalkan itu dengan sengaja. Mereka, seperti kita semua, adalah korban dari penilaian keliru dari diri mereka sendiri.
Ini akan membuat kita sadar pada paradoks Stoisisme yang lain: tidak ada yang memilih untuk sedih, stres, marah, sengsara. Semua ini sebenarnya adalah hasil penilaian kita atau satu hal yang ada dalam kendali kita.
Menerima Kenyataan
Prinsip Stoic terakhir adalah mengingatkan diri tentang posisi relativitas kita. Kita harus paham bahwa dunia tidak berputar di sekeliling kita. Aurelius secara teratur melakukan meditasi, bercermin tentang luasnya alam semesta dan menelaah posisi waktu yang merentang dari masa lalu juga ke masa depan. Ia, secara kontemplatif, menempatkan jangka kehidupan pendeknya ke dalam konteks yang lebih luas.
Aurelius berpikir bahwa kehidupan kita terbatas dalam saat kita ditempatkan dalam perspektif kosmik ini. Lewat cara itu, ia terus bertanya-tanya: mengapa kita harus mengharapkan alam semesta memberikan apa pun yang kita inginkan? Sangat tidak masuk akal untuk mengharapkan semesta selalu sesuai dengan kehendak kita.
Seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu berharap alam semesta memberikan apa pun yang kamu inginkan, kamu akan kecewa, tetapi jika kamu mendekap apa pun yang diberikan alam semesta, hidup akan jauh lebih bahagia.
Tiga prinsip inilah yang membuat Stoic begitu relevan dan dekat dengan kehidupan urban dewasa ini. Alih-alih pusing menyatukan frekuensi dengan orang lain, Stoic lebih berfokus kepada memahat asumsi atas hal-hal yang terjadi terkait dengan diri kita dan bagaimana sikap kita atasnya. Memang betul bahwa soal ini tak mudah dilakukan. Tetapi, mereka yang telah melatih diri dan persepsi ini terbukti bisa, meskipun perlahan-lahan, membangun kebahagiaan hakiki di kemudian hari.
Related

Eksperimen Soderberg Lewat Unsane
You May Also Like



One Comment
Zaki
Wah saya tahu tentang stoicism karena buku Henry Manapiring yang Filosofi Teras, menarik nih mas. Makasih udah berbagai.
Kalau mau baca seputar fotografi silakan mampir ke blog saya ya.