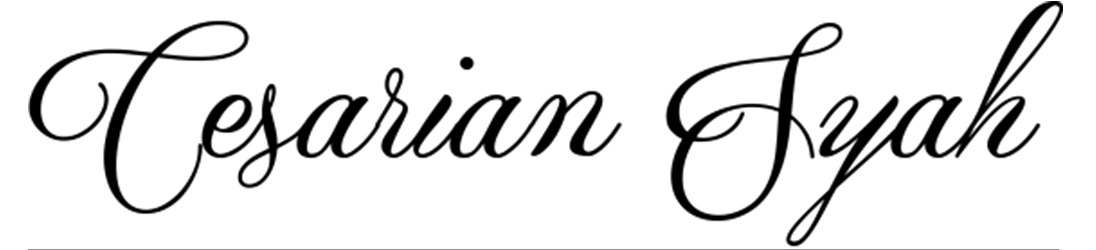Pulangkah Kita?
Tenanglah.
Aku tak pernah mengharap oleh-oleh
dari orang yang hidupnya susah.
Kamu bisa pulang dengan rindu yang masih utuh saja
sudah merupakan berkah.Pulang ya pulang saja.
Tak usah repot-repot membawa buah tangan
yang hanya akan membuat tanganku gemetar
dan mataku basah.(Surat Pulang – Joko Pinurbo)
Dua windu lalu di Paris, seorang lelaki tua menghirup udara lamat-lamat sebagai bagian napasnya yang terakhir. Saat itu, Ia berada jauh dari tanah airnya yang amat ia rindukan. Ia tidak bisa pulang. Ada jarak yang ingin ia tempuh namun tak mampu ia rengkuh. Lelaki itu, Dimas Suryo, akhirnya tumpas sebelum mencecap rasanya pulang. Kematian datang untuk menjemputnya terlebih dahulu. Ia memang pulang, tapi tidak menuju tanah air. Ia diajak pulang ke tempat paling asali.
Kisah itu hanya rekaan Leila S. Chudori dalam novelnya, Pulang. Tapi, dari kisah itu, kita bisa memahami bahwa kata pulang, dalam babak akhir kisah hidup Dimas Suryo, memiliki dua arti. Pertama, ‘pulang’ yang berada dalam koridor makna ‘menuju sebuah tempat’. Kedua, ‘pulang’ yang memiliki arti ‘meninggal’. Dua arti itu hanya sedikit dari banyaknya definisi yang bisa kita peras dari sebuah kata ‘pulang’ .
“Pulang adalah sebuah transit melalui keberbedaan,” seru Martin Heidegger dalam kuliahnya, The Ister, yang mengupas sajak milik Friedrich Hölderlein. Sajak Hölderlein berisi metafora sungai Danube sebagai tempat tinggal, perjalanan, dan aliran kehidupan manusia. Aliran sungai, sebagai manifestasi sebuah perjalanan, akan menempa manusia untuk menjadi lebih bersahaja. Rangkaian langkah-langkah kaki sepanjang perjalanan akan membuat manusia memahat nasib dirinya, atau, dalam ucapan Heidegger, pulang menemui rumah yang ia bangun.
Dalam perjalanan pulang, manusia akan bersua dengan liku yang tidak selalu akan dikenal. Kita akan melewati waktu dan tempat yang berbeda nuansa. Seperti kita yang pada tiap sore, selepas kerja, dalam kendaraan yang melaju di atas garis-garis jalan kota, melihat langit yang berganti-ganti cuaca. Di suatu pulang, kadang langit terlihat pekat setelah bergulat dengan badai dan membangkai gulita. Di pulang yang lain, kadang kita melihat langit yang cerah dan membingkai senja.
Sesampai di tempat yang kita sebut sebagai rumah pun, perjalanan belum usai. Keberadaan kita hanyalah sebuah mampir sebentar untuk kemudian menelusuri jengkal perjalanan yang berbeda lagi, dan akan menemui sebuah rumah yang tidak akan sama lagi. Walhasil, perjalanan pulang adalah kecemasan terhadap sebuah tempat yang akan dijelang. Bisakah sebuah pulang akan menemukan rumah yang sama ketika setiap kepergian adalah sesuatu yang berbeda?
Rumah menjadi sesuatu yang akan terus dibangun dari pulang demi pulang. Ia terdiri dari memori, kealpaan, kemurungan, kegembiraan, dan keberbedaan yang tidak kekal. Tiap pulang, kita akan menumpuk bata-bata emosi yang berbeda, menyusunnya, hingga pada akhirnya kita akan melihatnya jadi sebuah bangunan megah penuh kisah.
Namun ketika bangunan itu kita pandangi setelahnya, banyak kisah yang ternyata telah tumpah ruah. Kita akan menemukan kisah kita di sana, bercampur dengan kisah-kisah berlainan dari orang-orang lain yang juga pernah singgah atau berumah di dalamnya. Lewat kisah-kisah itu, kita pun memahami bahwa setiap pulang adalah narasi dengan makna yang personal.
—
Menyoal pulang, saya teringat tentang kisah sepuluh tahun lalu, tentang langit pucat serona dinding gedung tua kampus itu: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kala musim hujan tiba, cakrawala itu jarang sekali berubah warna. Gelap melekatkan diri padanya semenjak fajar hingga senja. Ketika hujan benar-benar datang, matahari tertutup dan sinarnya ¬tenggelam entah ke mana.
Di saat-saat itu, saya takut keluar kos. Hujan akan membuat parit di gang-gang menuju kampus meluap. Tak hanya itu, atap-atap rumah yang tidak tertata rapi akan membelokkan air dan mencucurkannya ke arah tubuh-tubuh para pelintas, seperti saya, tanpa mampu diduga. Perlu banyak peranti yang harus saya bawa supaya bisa sampai ke kampus dengan selamat.
Saya tak sendirian menelan kekhawatiran. Setidaknya, 33 orang lain punya perasaan yang sama. Malam sebelumnya, konfirmasi kehadiran dosen sudah disebarkan lewat jaringan pesan singkat dari ponsel ke ponsel. Pukul 08.00 pagi, kuliah harus sudah dimulai. Datang terlambat berarti siap menerima aneka hukuman.
Waktu sudah menunjukkan pukul 07.30 dan langit masih gulita. Sementara, gang di depan kos saya sudah digenangi air setinggi mata kaki dan hujan masih belum mau berhenti. Gemuruh guntur dan kejapan kilat juga sahut menyahut. Seakan tak cukup, angin kencang berhembus dan membawa percik hujan menyambar apa saja.Tembok, tiang listrik, hingga baju para pejalan kaki. Dengan hanya memiliki piranti berupa satu buah payung, perjalanan keluar kos sekarang berarti siap menyerahkan tubuh pada nasib kebasahan di kampus.
Akan tetapi absen kuliah juga bukan sebuah pilihan yang patut. Ada tiga mata kuliah akan diajarkan hari itu. Jika hujan tidak berhenti seharian, bisa-bisa jatah bolos tiga mata kuliah amblas sekaligus.
Maka keputusan pun diambil. Berangkatlah saya sambil menenangkan diri dengan persepsi bahwa teman-teman saya juga merasakan kepayahan yang sama. Mereka juga bakal nekat menembus hujan segila ini dan sajian kebasahan komunal akan tampak dalam ruang kelas.
Pada sebuah gang di Kalimongso, antara warung-warung makan yang menguarkan aroma masakan siap santap, saya berjingkat menghindari cucuran air dari atap-atap rumah. Beberapa teman sekelas turut berjingkat di depan dan belakang saya. Kami mengomel soal kemalasan menghadiri kuliah di tengah badai seperti ini. Meringkuk di dalam selimut, yang biasanya berupa selimut rumah sakit yang bergaris-garis hitam atau hijau, lebih masuk akal untuk dilakukan. Tapi, toh kami ada di sana. Di tengah-tengah tempias hujan yang berloncatan di atas atap dan uar bau masakan warteg, sambil bersandal jepit dan memegang payung serta mencangking plastik berisi sepatu dan kaos kaki yang entah kapan terakhir kali dicuci.
Hujan masih menabuhi jendela ketika ruang kelas sudah hampir penuh. Hanya dua atau tiga orang saja yang belum tampak. Terdengar suara sepatu ketua kelas kami yang sedang mondar-mandir. Ia mencoba menelepon dosen, yang sayangnya, selalu dijawab dengan nada sibuk. Waktu menunjukkan tiga puluh menit berlalu dari pukul 08.00. Mata kuliah pertama belum dimulai sementara waktu pergantian sesi terus mengejar.
Babak itu berulang terus hingga sebuah pesan singkat dari dosen masuk ke ponsel ketua kelas. Mata kuliah pertama ditiadakan karena lalu lintas macet luar biasa. Seisi kelas pun berada di perpaduan geli, jengkel, gondok, dan lega. Lontaran-lontaran tawa terdengar disertai celotehan kekecewaan tentang usaha menerobos hujannya yangsia-sia. Namun tidak semuanya disajikan secara serius. Episode itu hanya berakhir dengan obrolan ngalor ngidul sembari menunggu mata kuliah selanjutnya—yang kemudian turut dibatalkan juga.
Rangkaian cerita itu sudah sedemikian lazim terjadi dan menjadi salah satu kisah khas kampus yang melulu saya ingat. Ia menjadi bata penyusun dinding-dinding bangunan yang, ketika saya kembali ke kampus, masih bersuara dan akan selalu saya kenang.
Masih banyak cerita lainnya dalam dinding kampus itu. Tentang tubuh seseorang yang diseret dan diarak dari gedung kampus untuk dilemparkan ke dalam kolam warga ketika ulang tahun, tentang amuk dosen karena mengenakan seragam dengan warna-warna tertentu, atau tentang seekor kambing yang melompat dari lantai 3 dan difatwa sebagai upaya bunuh diri.
Narasi-narasi itu sangat personal walapun dibentuk oleh banyak orang. Saya masih ingat sebagian wajah-wajah teman-teman saya, yang berada dalam tawa dan kegelian, ketika melemparkan saya ke kolam. Saya juga masih ingat air muka kekecewaan mereka saat kalah dalam pertandingan sepakbola antar kelas. Tapi, narasi itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Setiap orang bisa mengingat kejadian yang sama atau berlaian dengan detil tapi detil ingatan yang juga beraneka rupa.
Pelbagai ingatan itulah yang terakumulasi dan membentuk sudut pandang kita tentang kampus kita. Itulah bata-bata yang kita tumpuk sehingga kenangan akan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara bisa bisa berisi aneka cerita soal kedigdayaan masa muda, repetisi gerak antara kampus dan kos saja, atau jalinan pertemanan yang kuat dan bergelora, hingga awal mula hidup yang lebih sejahtera.
Dan ketika kita berdiri tempat kita sekarang, tempat yang kadangkala kita sebut sebagai rantau, kita akan melihat STAN sebagai sebuah rumah yang ditinggalkan dan sesekali dikunjungi. Emosi kita mungkin masih terikat di paras gedung dan tamannya walau, sayangnya, kita jarang menyempatkan untuk datang dan mencoba menikmati emosi-emosi yang telah bertaut itu.
Padahal, episode kampus juga adalah aliran Sungai Danube. Ia bagian dari perjalanan kita menuju diri. Episode itu turut memahat sikap kita. Dan tanpanya, kita bukanlah kita yang sekarang.
Maka, kehendak untuk sesekali berbalik mengunjungi kepulangan pada rumah itu perlulah diwujudkan. Sebentuk ziarah, kita bisa menemui sosok-sosok yang pernah kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Melalui pertemuan-pertemuan kembali juga, kita bisa mengenal ulang dan menertawakan tingkah kita saat menghadapi kecemasan-kecemasan masa lalu.
Mungkin, lewat pertemuan kembali pula kita bisa menggenggam lagi kebahagiaan dan merasakan kenyamanan yang pernah dicecap. Kita akan transit dan berbagi canda sejenak sebelum berangkat lagi menemui keberbedaan.
Pertemuan kembali itu adalah momen personal menjemput kepulangan-kepulangan, sehingga ia tidak perlu dilaksanakan dengan pakaian yang gemerlap. Kita tidak perlu, seperti sajak Joko Pinurbo, repot repot membawa buah tangan—apalagi berupa keletihan atau kegundahan pekerjaan—walau mungkin tetap saja bakal ada hal-hal lain yang membuat tangan gemetar dan mata basah. Kita bisa menanggalkan semua pakaian itu (tekanan, pikiran, stres?) dan kembali pada bangunan tempat kita pernah dibesarkan. Tempat yang kita tinggalkan berkali-kali tetapi selalu ada ketika kita butuh kembali.
Jadi, pulangkah kita?
post scriptum: ditulis sebagai prakata Reuni Akbar Ikatan Alumni Kedinasan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2016
Related
L'etranger: Sang Liyan
You May Also Like

Pesan-Pesan dari Poso
27/12/2016
Dolanan yang Memugar Ingatan
10/08/2016