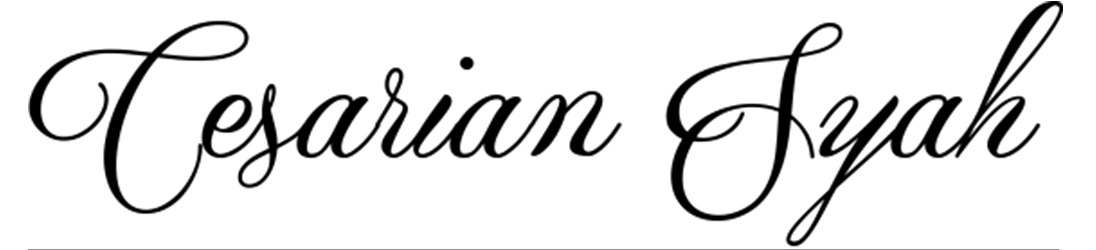L’etranger: Sang Liyan
Resensi buku Orang Asing karya Albert Camus
“Supaya semua tereguk, supaya aku tidak merasa terlalu kesepian, aku hanya mengharapkan agar banyak penonton datang pada hari pelaksanaan hukuman matiku dan agar mereka menyambutku dengan meneriakkan cercaan-cercaan.”

Kalimat sangat satir dan menggambarkan destruktivitas sekaligus konstruktivitas sebuah perasaan seorang terpidana mati tergurat lembut di halaman terakhir buku ini. Selarik kalimat tersebut juga menjadi senjata pamungkas yang tepat dalam fitrahnya sebagai representasi novel “Orang Asing” ini secara utuh. Rangkaian kata-kata tersebut nampak asing dan mengemukakan sebuah sikap yang teralienasi dan berada jauh dari tapal batas yang dibentuk oleh persepsi kewajaran. Berdasarkan basis itu pula, Camus mengintisarikan sebuah kisah yang ekletik dengan poros sebuah benda abstrak yang terus dipertanyakan: kebenaran. Camus mengetengahkan seseorang tokoh yang tidak hanya liyan, tetapi betul-betul berusaha menjalani ke-liyan-an yang wajar dalam institusi hidupnya. Penahbisan tokoh utama bernama Meursault dalam gelanggang hidupnya menjadi sentral dan menarik untuk ditelisik lebih dalam, terutama dalam kacamata eksistensialisme.
Saya mengutip Jeannyves Guerin dalam pernyataannya bahwa dalam pandangan pendekatan moral-filosofis, Albert Camus “hanya dapat dimaknai secara utuh apabila kita mengetahui eksistensialisme.” Berpijak pada remah frase tersebut, karya monumental Camus ini harus dibaca dengan mengenakan kacamata eksistensialisme. Jika tidak, rangkaian kata yang kita kunyah hanya sebuah kehambaran. Kita hanya akan membaca catatan harian seorang yang aneh dan tragik, tanpa mengetahui hakikat yang berperang di dalamnya.
Eksistensialisme memandang manusia sebagai sebuah institusi yang sadar akan dirinya. Ketersadaran itu membuat ia bisa berada di dalam diri sekaligus ada di luar dirinya (terutama dalam kaidah penilaian diri). Pemosisian diri seperti ini membuat manusia seperti makhluk terbatas yang dihamparkan di padang ketidakterbatasan kehidupan. Keterbatasan yang dikepung ini menjadi pangkal dari penafsiran diri menjadi sesuatu yang sia-sia jika dimaknai. Tiap usaha manusia menakrifkan kehakikian hidup digiring menuju ambang kegagalan. Karena batas yang ada pada manusia tidak mampu memenuhi relung ketidakterbatasan nasib kehidupan. Akhirnya yang dirasakan hanya perspektif ketanpaartian, tanpa tujuan, tanpa arah, dan pertanyaan akan hidup yang takkan pernah selesai.
Kebenaran, sebagai poros dari jenis pemahaman ini menjadi sebuah hasil doktrinasi yang didekonsktruksi. Mudahnya, ia dipecah menjadi puing-puing yang lebih bias di mana setiap puing dipertanyakan hakikatnya. Puing tersebut tidak bisa dipaparkan secara hitam putih. Eksistensialisme menolak kebenaran mutlak. Tiada kebenaran yang hakiki yang lahir karena doktrin. Manusia dianggap sadar sehingga mereka mampu menentukan kebenaran hakikinya. Oleh karena itu, Kierkegaard, bapak eksistensialisme, menulis diri manusia sebagai objek sekaligus subjek kehidupan secara kontinu. Kebenaran tidak disimplifikasi dari hasil konsensus masyarakat, namun harus ditemukan dan dijalani. Di salah satu tulisannya, Kierkegaard menulis “the highest and most beautiful things in life are not to be heard about, nor read about, nor seen but, if one will, are to be lived.” Hal paling asasi dari kehidupan lahir jika manusia menjalani hidupnya sendiri.
Dalam “Orang Asing”, Meursault digambarkan sebagai manusia antinorma -bahkan di dalam sebuah dialog, ia dicap anti Kristus – yang menjalani hidup wajar (menurut cara pandangnya) namun aneh (jika dihadapkan pada konsensus umum). Pada awal novel, deskripsi tersebut telah hadir dan berbunyi:
Hari ini Ibu meninggal. Atau, mungkin kemarin, aku tidak tahu. Aku menerima telegram dari panti wreda: “Ibu meninggal. Dimakamkan besok. Ikut berduka cita.” Kata-kata itu tidak jelas, mungkin ibu meninggal kemarin.
Aposisi kalimat ini secara liar mempertanyakan kehidupan seorang anak yang seakan melupakan ibunya dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Meursault acuh atas kematian ibunya, dan terlihat tidak peduli akan nasib ibunya hingga persoalan meninggal kemarin atau kemarinnya lagi tidaklah begitu penting. Dalam keberlanjutan kisahnya, Meursault digambarkan lebih liyan. Ia tidak menangis saat pemakaman ibunya, berhubungan dengan kekasihnya tepat sehari setelah pemakaman, dan lebih sibuk mengomentari kecapan-kecapan penghuni panti jompo dibandingkan mengurus jenazah ibunya. Tapi Meursault juga satir dalam kalimatnya, “Aku bahkan mendapati kesan bahwa jenazah itu, yang terbaring di tengah mereka, tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka.” Padahal, dalam ruang duka, Meursault sendiri tidak menangis – yang menyebabkan kita berpikir, jangan-jangan jenazah Ibunya pun tak berarti bagi dirinya -.
Camus kemudian menggambarkan liku hidup Meursault menjadi rangkaian yang banal: menolak pernikahan sebagai sebuah lembaga dan memandangnya sebagai ritus belaka (Ia mengafirmasinya dengan janji mengatakan “iya” pada siapapun wanita yang mengajaknya menikah), hidup bersisian dengan orang-orang yang sinting (Salamano tua yang sadis pada anjingnya atau Raymond yang seorang germo), serta melakukan pembunuhan sadistik (tetap menembaki orang yang telah dibunuhnya sebanyak empat kali).
Protogoras menciptakan istilah homo mensura, yaitu manusia sebagai tolok ukur. Dalam eksistensialisme absurditas ala Camus, tolok ukur manusia lahir dari kegagalan inheren manusia untuk memahami hidupnya. Akibatnya, hidup dijalani secara absurd sambil menuju pada satu kepastian mati dan tolok ukur tadi menjadi tidak pasti pula. Melalui bibir Meursault, absurditas ini tergambar jelas ketika ia sendiri menggambarkan kematiannya dengan kata-kata “Pada hakikatnya aku tahu bahwa mati pada umur tiga puluh atau enam puluh tahun tidak begitu penting, karena tentu saja dalam kedua kasus itu laki-laki dan wanita lain akan tetap hidup, dan itu terjadi selama ribuan tahun.” Iya, kematian didefinisikan menjadi variabel tanpa peubah, di mana tidak akan terpengaruh atau mempengaruhi kematian orang lain. Dalam falsafah ini, tolok ukur menjadi bukan hanya “tidak pasti” melainkan “tidak penting”. Setiap manusia bisa membuat tolok ukurnya sendiri.
Tentu saja benturan laku Meursault dengan kenyataan hidup menjadi akhir yang sempurna dalam novel ini. Kejahatan pembunuhan yang diseret di depan muka persidangan menjadi apik ketika Meursault dalam kesadarannya membantai sikap hidup yang tragik sekaligus nostalgik. Ia merekonstruksi sisa-sisa harapan yang dimiliki menjadi bangunan utuh tempat ia berlindung. Meursault menjadikan dirinya objek yang sanggup menjalani ketidakbiasaan menjadi sebuah kebiasaan. Ia menolak pengakuan dosa dan memilih menikmati waktu yang tersisa sebelum dihukum mati.
Meursault dianalogikan sebagai tokoh Sisifus yang mendorong batu ke atas bukit untuk hanya melihatnya menggelinding kembali ke bawah kembali dalam sebuah hukuman yang abadi (Hal ini tercermin dalam kumpulan esai Cerita Sisifus, juga karya Camus). Hukuman yang merepresentasikan kesia-siaan. Di padang kesia-siaan yang begitu luas, Camus lewat Meursault mengambil sudut pandang berbeda. Ia menggamangi sebuah harapan, di mana ketika Sisifus turun setelah mendorong batu ke puncak bukit, ada harapan agar batu itu tidak menggelinding kembali ke bawah. Harapan semacam ini yang dieksploitasi oleh Camus lewat penggalan renungan Meursault: “Kita selalu membayangkan secara berlebihan sesuatu yang tidak kita ketahui.” terkait dengan “…aku melihat bahwa yang tidak sempurna pada pisau pemenggal, adalah bahwa tidak ada kesempatan, sama sekali tidak ada.”. Ya, dalam keterperaman luka yang sejati pun manusia masih mencari kesempatan akan adanya harapan.
Maka, sejatinya hidup dalam perspektif L’etranger adalah hidup yang liyan: berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Meursault adalah orang yang memandang kehidupan sebagai, mengutip kata-katanya sendiri, sebuah pintu kesengsaraan. Absurdisme memandang kematian sebagai sebuah pembebasan. Dalam “Orang Asing”, kematian justru dirayakan sebagai sebuah persiapan untuk hidup kembali. Hidup dari kesengsaraan mati di dunia. Perihal yang menjadi suatu oposisi sempurna dari sebaris sajak Chairil : Hidup hanya menunda kekalahan. Mungkin Meursault justru akan mendatangi Chairil dan berucap: “Tidak ada yang kalah dalam hidup, seperti halnya tidak ada yang menang, Ril. Hanya kematian yang sepenuhnya datang menghampiri.”
Related

Dolanan yang Memugar Ingatan

Pulangkah Kita?
You May Also Like
Bukan Sedu Sedan, Melainkan Keredupan Kehidupan
15/02/2017
Perangkap Pesona Pokemon
23/07/2016