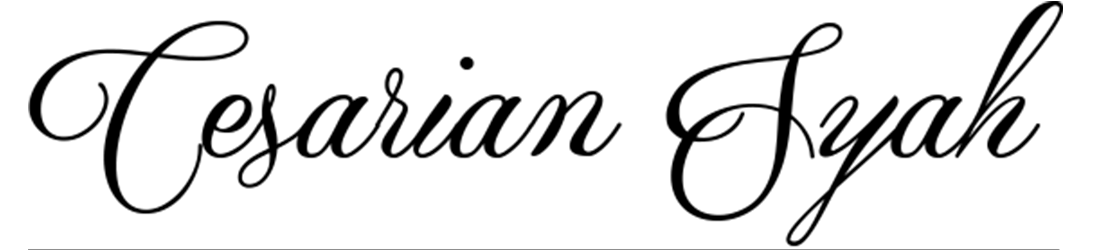Merayakan Gelak Puisi Beni
Coba kau tanyakan sepuluh orang di dekatmu tentang nama Beni Satryo dan dengarlah jawaban mereka. “Tidak kenal” atau “Siapa ya?” barangkali jawaban paling sering kau dapatkan. Padahal namanya sangat galib. Beni dan Satryo sangat sering dipakai sebagai nama — keduanya bahkan umum digunakan sebagai nama panggilan. Tapi begitu kedua nama itu dipadukan, kebanyakan dari kita akan bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya dia.
Beni Satryo, si empunya nama, sesungguhnya mewarisi kegaliban namanya. Ia adalah orang biasa dengan kegiatan biasa yakni hilir mudik menjadi seorang wartawan. Jikalau ada yang berbeda dari Beni, tak lain adalah soal lelaki kurus berkacamata itu yang mendaku bershio gabah dan mahir menulis pwissie. Belakangan, Beni menghimpun serakan pwissienya ke dalam sebuah buku pwissie berjudul “Pendidikan Jasmani dan Kesunyian”.
Pwissie adalah slang dari kata puisi. Pwissie mungkin juga menjadi istilah yang Beni tabalkan untuk puisi-puisinya. Beni acap mengganti u dengan w. Di jagad twitter sendiri, Beni sering memplesetkan kata luar biasa menjadi “warbyasak~”, tingkah yang ditularkan kemudian kepada kata-kata lain, termasuk mengubah puisi menjadi pwissie.
Plesetan puisi menjadi pwissie juga menyiratkan tawa yang berkembang di dalam nomina itu. Beni seakan mencoba membedakan pwissie dari puisi. Puisi, yang konon dikuasai tutur bahasa yang tinggi, dirayakan Beni dengan lebih sederhana. Beni, yang memang menyukai humor, membawa unsur gelak ke dalam puisi-puisinya. Ia tidak menggunakan alegori atau perumpamaan yang megah, tetapi mencomot apa saja yang ada di sekitar dirinya menjadi bahan utama. Puisi pun luruh menjadi sesuatu yang lucu sekaligus lumrah dan dekat. Seperti puisi “Di Restoran”.
Kau bertanya banyak hal
saat kita mampir di restoran ituIni apa? Lada.
Ini? Garam dan saus.
Itu apa? Pisau dan garpu.
Itu?Kau menunjuk sesuatu yang mengalir
dari kedua mataku yang hambar.
Aku menunjuk struk-struk yang terselip
di bawah mangkuk acar.Itu apa? Harga yang harus kita bayar.
“Di restoran” menyajikan narasi lucu tentang dua orang muda-mudi yang berkencan di restoran. Latarnya adalah keluguan seorang kekasih yang bertanya saking banyaknya hingga membuat pasangannya kesal. Persoalan dipungkasi tentang membayar makanan yang baru saja disantap, sebuah problematika keseharian muda-mudi. Di sana, Beni menghadirkan cerita itu begitu saja tanpa dipersolek melalui kata-kata yang wah, dan menjadi semacam antitesis puisi berjudul sama dari Sapardi Djoko Damono.
Makanan, agaknya, berpengaruh besar dalam puisi-puisi Beni. Dalam Pendidikan Jasmani dan Kesunyian, tak kurang 23 dari 58 puisinya mengandung nama makanan. Beberapa makanan bahkan didaulat menjadi judul puisi, yaitu “Ledre”, “Telur”, “Klepon”, “Onde”, “Nagasari’, “Permen Yupi”, dan “Mie Cakalang”. Di puisi-puisi itu, makanan terkadang dihadirkan sebagai sebuah perumpamaan seperti dalam “Mie Cakalang”.
Ah, hatiku yang mie goreng cakalang
diunyel-unyel garpumu yang jalangItupun tak kau makan
Namun, di puisi lain ia menaruhnya sebagai subjek yang diceritakan. Puisi “Permen Yupi” contohnya:
Di dalam hatiku
Ada seekor permen yupiSedang mengunyah dirinya sendiri
Tidak hanya menjadi menu utama dalam puisi, Beni memperlebar latar dari makanan ke tempat hingga alat menyantapnya. Seperti puisi “Di Restoran” yang membuat cerita berlatar sebuah tempat, Beni juga menulis larik lucu tentang perkakas makan dalam “Tenda Biru”.
Pergilah! Kejarlah keinginanmu untuk menjadi
bakul pecel lele. Saat air kobokan di meja-mejamu mulai keruh, kenang, kenanglah aku.Sebagai kemangi yang mulai layu.
Beni begitu mahir merontokkan imaji cinta yang sering tercermin agung sekaligus perih lewat kata-kata hujan, senja, atau mentari. Alih-alih mengikuti arus dengan menggunakan kacamata urban, ia lebih memilih bakul pecel lele, kemangi, dan kobokan untuk mengisahkan sudut pandangnya akan cinta. Tentu pemilihan benda-benda tadi paralel jua. Agak aneh jika bakul pecel lele tiba-tiba mengasosiasikan cinta dengan gunung dan ngarai, tempat yang tak lazim bagi bakul pecel lele berjualan.
Selain itu, melalui puisi-puisinya Beni menyiratkan posisinya yang berada di antara manusia-manusia rural, yaitu mereka yang berpredikat kelas bawah dan menengah Indonesia. Mereka yang berjumlah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Mereka yang lebih sering melewati trotoar dan mengantri angkutan. Beni dengan penuh kesadaran memilih menceritakan liku-liku hidup mereka yang lugu dan apa adanya. Dengan pijakan seperti itu, puisi Beni bisa lahir dan melancong dari restoran (puisi “Di Restoran”), bakul pecel lele (puisi “Tenda Biru”), metromini (puisi Di “Metromini”), angkutan kota (puisi “Dari Dramaga, Kita Pernah Satu Angkot”), bahkan dari bak cuci piring (puisi “Bak Cuci Piring”). Salah satu puisinya yang kuat juga berasal dari tempat yang jamak disebut kala musim mudik: “Di Pantura”.
Di Pantura,
Air mata dan samudera mesra berkawin.
Berbulan madu di cakrawala
Menjadi sebutir telur asin.
Saat menanak puisi-puisinya, Beni mengambil pendekatan yang mirip dengan pendekatan yang dilakukan oleh Joko Pinurbo. Keterampilan Jokpin, panggilan Joko Pinurbo, mempermainkan kata-kata diseruput dalam-dalam dan dimuntahkan oleh Beni dalam serat katanya. Nuansa yang ditampilkan Jokpin dalam puisi “Ranjang Kecil” misalnya, yang berbunyi Tubuhmu tak punya lagi ruang/ ketika relungmu menghembuskan raung// dengan mudah terasa dalam puisi “Peluk Luka”.
Seorang penyair kelimpungan
mengejar huruf A yang lari dari puisi-puisinya.Huruf itu angslup ke dalam sebuah peluk
Lalu menjadi peluka.Lalu luka.
Nuansa yang sama bisa ditemukan dalam puisi “Korintian”, “Pencuri Akhir Pekan”, “Obat Tidur”, “Aduh”, ataupun puisi yang menjadi judul buku ini “Pendidikan Jasmani dan Kesunyian.”
Tapi tentu saja tidak semua puisi Beni beraroma Jokpin. Dalam “Bandung 1” dan “Bandung 2”, Beni memiliki tapal tempat ia mendirikan keromantisannya sendiri. Selain itu, tempat bermain-main Beni dan Jokpin sungguh berbeda. Puisi Jokpin kian sarat akan kritik sosial, sementara Beni menyajikan tawarnya kehidupan yang bergerak di sekelilingnya. Beni, yang konon pernah mengasong puisi, luwes bermain-main di tema yang menyangkut derita-derita kecilnya. Ia tidak memaksakan untuk mencoba berfilsafat atau menyasar ke tema lain yang asing.
Walaupun begitu, di tema itulah Beni bisa tampil sebagai Beni. Dengan humor, ia membuat potret sebagian besar kita. Sebagian potretnya bahkan mengangkat hal-hal yang luput dari indera kita padahal kita enyam sehari-hari, hal-hal yang berada sedekat tengokan kepala kita, serta hal-hal yang kita terima begitu saja tanpa tapi.
Seperti halnya asongan, Beni menjaja apa yang sebenarnya kita butuhkan walaupun dengan banyak alasan kita sering memalingkan muka padanya. Padahal mengonsumsi puisi Beni adalah membaca kealpaan kita sendiri. Puisi Beni adalah himpunan suara-suara, baik suara manusia maupun benda, yang tidak didengar dengan penuh seluruh. Dengan memungut kata sederhana, merajutnya, dan memberikan sentuhan humor, Beni sejatinya menulis sebagai perayaan atas gelak puisi yang mengendurkan otot-otot rindu, sekaligus aktivitas yang bisa mengencangkan air matamu.
Lain kali, jika kamu sedang bertandang ke tenda-tenda penjaja tanpa tamu, longoklah ke dalam. Siapa tahu kamu bisa menemui Beni dalam tenda-tenda yang wajah bakulnya sudah kau lupakan itu.
Related
Kita dan Benda-Benda
Gurun Puisi WS Rendra
You May Also Like

Gula Kacang
26/01/2016
Insentif Pajak yang Cantik dan Produktif
06/07/2018