Untuk Kamu yang Begitu Dekat Namun Seakan Begitu Jauh

sebuah tanya tentang kematian
supaya ridla menerima segala tiba
Untuk sesuatu yang begitu dekat intaiannya, kematian sering menjadi sebuah hal yang teramat asing. Bukan hanya karena kita tidak ingin mengenalnya, melainkan juga karena kita tidak mampu mengenalnya. Raut kematian serupa kegelapan senyap atau ketiadaan hakiki. Di dalamnya tinggal sebuah tanya yang gamang. Tanya seluas segara kehidupan yang melengkung, namun tidak diketahui muara dari lengkungan itu sendiri.
Kematian, bagi sebagian orang, sama menariknya dengan lazuardi yang gagah-gemerlap-berkilauan. Ia memikat sebagian orang untuk menggerai tirai-tirai rahasianya yang tertutup. Keingintahuan, menyeret akal kita untuk menyingkap tirai tersebut dan memahami apa yang ada di baliknya.
JIka kehidupan terasosiasi dengan kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, dan aneka kenisbian lainnya yang secara parsial saling melekat, apakah dibalik tabir kematian itu hanya terdapat kebalikannya? Ataukah segala kenisbian akan hilang dan terdapat kepastian belaka?
Manusia, menurut Gabriel Marcel, adalah sebuah mystere, gugus yang tidak mungkin sifat dan cirinya dapat diselesaikan secara tuntas. Manusia diberikan sebuah kesadaran untuk memilih diantara padang kehidupan yang luas. Pilihan, akan mengidentifikasikan manusia ke dalam kelas-kelas tertentu, sekaligus menceraikannya dengan piihan manusia lain. Sebuah pilihan akan mereproduksi sebuah sifat yang tertanam pada diri, serta memiliki konsekuensi logis yang entah dapat diselesaikan atau justru berkembang biak dengan pilihan-pilihan selanjutnya.
Kehadiran sebuah pilihan dalam hidup, jika ditinjau secara dialektik, terasa anomali karena manusia tidak diberikan pilihan ketika “dipaksa” menyambut hidup dan kehidupan. Manusia, yang sekarang berenang dalam danau kehidupan, tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Padahal, ketika manusia sudah berjalan di dalam gelora kehidupan, kematian dapat menjemput tanpa terlebih dahulu mengetuk pintu. Kematian datang sebagai sebuah realitas pahit, merenggut keindahan dunia yang sudah digelorakan dan diselami. Kematian yang datang ini adalah sebuah paradoks dari pilihan-pilihan yang diberikan selama hidup. Kita tidak bisa memilih kapan kita akan menemui kematian.
Secara umum, manusia menganggap kematian adalah sebuah kekalahan. Kekalahan dari pertarungan yang disediakan dari pilihan-pilihan hidup. Ia hanya akan meletakkan manusia kembali kepada kodratnya yang teralienasi: sebuah otoritas yang hanya mewakili pribadinya.
Fragmen kematian sebagai sebuah kekalahan ini seakan mengakar dan melekat di budaya kita. Realitas hidup yang dipenuhi kebebasan dipandang sebagai hal yang positif. Maka hidup difalsifikasi sebagai kemenangan semata.
Ironisnya, kesadaran hidup memiliki dua wajah, yaitu kebebasan diri sendiri dan ikatan terhadap tatanan nilai yang diusung oleh masyarakat. Kedua wajah itu pada hakikatnya saling meniadakan. Walaupun demikian, kehidupan tetap dipandang sebagai kemungkinan yang terbuka. Sebuah jalan dengan cabang-cabang yang tak terhingga banyaknya. Kehidupan (baca: kelahiran) tetap dirayakan.
Sedangkan dalam sketsa kematian, kemungkinan yang terbuka ditutup paksa. Jamaknya pilihan menjadi tidak berarti lagi. Manusia jatuh. Tidak heran jika di bangsal tempat raut maut mendekati manusia, acapkali kerabat di sekitarnya mendoakan agar sang manusia dapat “terus berjuang”, “bertahan”, atau “kuatkan diri” untuk tetap hidup, seakan kehidupan memang lebih gemerlap dibandingkan dengan kenihilan sebuah kematian.

Ketakutan manusia akan kematian disebabkan, menukil Sidi Gazalba, kesangsian yang muncul dari ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan kegelisahan dan pada akhirnya kegelisahan akan membawa manusia kepada kecemasan dan ketakutan.
Kematian, bagi Socrates, tidak serta-merta menutup pintu kemungkinan. Socrates menganggap kematian adalah sarana pembebasan bagi kemurnian jiwa. Tubuh yang dianggap sebagai penjara jiwa pada akhirnya tidak mampu mengurungnya lagi ketika kematian datang. Kemungkinan yang beruas-ruas dan bercabang-cabang memang tertutup, tapi ada sebuah jalan murni yang terbentang dan ditapaki nantinya.
Sartre, dalam kesinisannya berujar bahwa manusia dihukum untuk merdeka. Pilihan yang bebas justru menyodorkan kecemasan tertentu ketika secara sadar sebuah pilihan telah diambil. Kesadaran mengambil sebuah pilihan berarti kesadaran untuk menerima konsekuensi tidak dipilihnya pilihan yang lain. Ia menyebutnya la nausea, suatu perasaan muak yang aneh.
Pengetahuan intuitif menyunggi alam pemikiran kita untuk mempertanyakan tentang kehidupan yang lahir dari kematian. Dalam teori kuantum, setiap bagian dari semesta menyimpan informasi, termasuk bagian-bagian yang “kosong”. Manusia, sebagai bagian dari semesta, juga menyimpan informasi dalam sel-selnya. Informasi ini terikat-terkait dengan informasi yang ada di-luar-manusia. Jiwa, menurut Hameroff, difabrikasi dari struktur yang sama yang membentuk semesta. Oleh karena itu, ketika manusia meninggal, informasi yang disimpan masing-masing manusia, berpendar kembali ke semesta.
Dalam penelaahan fisik, kemungkinan kehidupan seperti itu tentu saja benar adanya. Jiwa kita menjadi bagian dari semesta. Namun, pada tataran metafisik, kehidupan setelah kematian dikonstruksikan secara imanen dengan surga dan neraka: pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan selama di dunia.
Jiwa, adalah nafas yang ditiupkan Tuhan kepada tubuh manusia. Di dalam jiwa, dimensi Tuhan hadir. Nafas ini, kelak akan diminta kembali oleh sang pemilik. Di situlah kematian muncul sebagai kehendak Tuhan untuk meminta kembali nafas-Nya. Realitas spiritual memainkan perannya di sini. Kematian, seperti halnya kehidupan, merupakan jalan yang harus diambil semua yang hidup. Setelahnya, keyakinan kita menuliskan ihwal pertanggungjawaban pelbagai pilihan yang telah diambil semasa hidup. Kematian, menjadi gerbang bagi kehidupan yang baru. Sebuah proses siklikal yang mungkin sama dengan kehidupan namun berbeda ruang dan waktu.
Persoalan unik dari kematian dalam tataran keimanan adalah balasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Kebaikan dibalas dengan surga, dan kejahatan dibalas dengan neraka. Intelektualitas kita menanyakan, bahwa kebebasan yang diberikan, sebenarnya dipertentangkan dengan nilai-nilai yang tidak hanya berada di masyarakat, namun juga nilai-nilai Ketuhanan yang transendental.
Di dunia ini segala sesuatu diberikan tanpa keterangan apa-apa, ungkap Camus. Setelah kematian, kita juga tidak mengetahui apa-apa. Lalu, manusia menghadapi rasa resah yang papa saat menghadapi kematian karena mereka takut akan kegelapan tanpa gugur, atau kesunyian tanpa tepi. Lantas, otoritas otak manusia membuat persepsi bahwa kematian akan menjadi hal yang tidak bermakna.
Socrates menjawab panggilan kematian dengan sukacita. Karena baginya, kematian adalah kebahagiaan yang hakiki. Jiwa, sebagai nafas Tuhan, akan terbebas dari tubuh yang melulu dikonstruksi-dekonstruksi melalui hal-hal yang ditabalkan padanya. Melalui kematian, Socrates menganggap kebutuhan atas pengetahuan dan kebahagiaan yang abadi akan tercipta. Pemenuhan ini, tentu saja, lebih sejati daripada memenuhi persepsi yang diukir orang-orang atas diri kita.
Di tengah tarik-menarik antara pengetahuan dengan keimanan, bukan tidak mungkin manusia menjadi hilang arah karena ketidaktahuan yang (mungkin) kekal. Saya teringat akhir episode Through The Wormhole kala membahas “Is there life after death” yang mengungkap parafrase: “mungkin sudah saatnya kita bergeser dari apa-yang-kita-ketahui menjadi apa-yang-kita-percayai”. Seiring fakta bahwa kematian tidak dapat diingkari serta pengingkaran terhadap kematian hanyalah kesia-siaan yang delusional. Sudah saaatnya kita mulai mengimani bahwa kematian akan membawa kebahagiaan yang lebih besar dari sebelumya. Ketiadaan adalah ruang yang misterius, dan hanya prasangka yang dapat mendorong kita berpersepsi bahwa kematian bukan sebuah kekalahan.
Kematian adalah sebuah perjalanan menuju ketiadaan bagi kehidupan fisik. Tapi, kehidupan memang bukan hanya kehidupan fisik semata. Kehidupan fisik hanya persinggahan, serupa mimpi yang menyiksa jiwa dalam beberapa bagian. Manusia, kita ibaratkan saja menuju sebuah kosmos noetos, sebuah dunia yang tidak terlihat namun dapat dipikirkan. Sebuah dunia yang bisa kita bayangkan sebagai dunia yang indah, tidak ada nafsu, dan penuh dengan kebahagiaan yang murni tanpa prasangkan dan tanpa tapi. Sebuah rumah, di mana semuanya berasal dan kembali pulang. Tempat di mana kebahagiaan dirayakan di atas baris tepi sunyi yang meneduhkan.
Post scriptum :
Saya menulis ini setelah membaca kumpulan sajak “Kematian Kecil Kartosoewirjo” dan menonton episode Through The Wormhole yang berjudul “Is There Life After Death”. Pemahaman atas kematian juga saya temukan di sajak-sajak Chairil seperti “Nisan” dan “Derai-derai Cemara”. Quote “ridla menerima segala tiba” juga saya ambil dari Puisi Chairil yang berjudul nisan. Untuk memahami sajak-sajak Chairil Anwar terkait pasang surut dan koyak lantak kehidupannya bisa membaca buku karya Arief Budiman berjudul “Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan”. Semoga kelak di akhir hidup kita, mengutip puisi “Raut Maut”, ada perahu dan malaikat yang mengantar kita pulang ke rumah penuh ayat. Saya tutup dengan amin yang sederhana.
Related
Didik
You May Also Like

Wae Rebo: Asyik Bercantik Sendiri
28/10/2017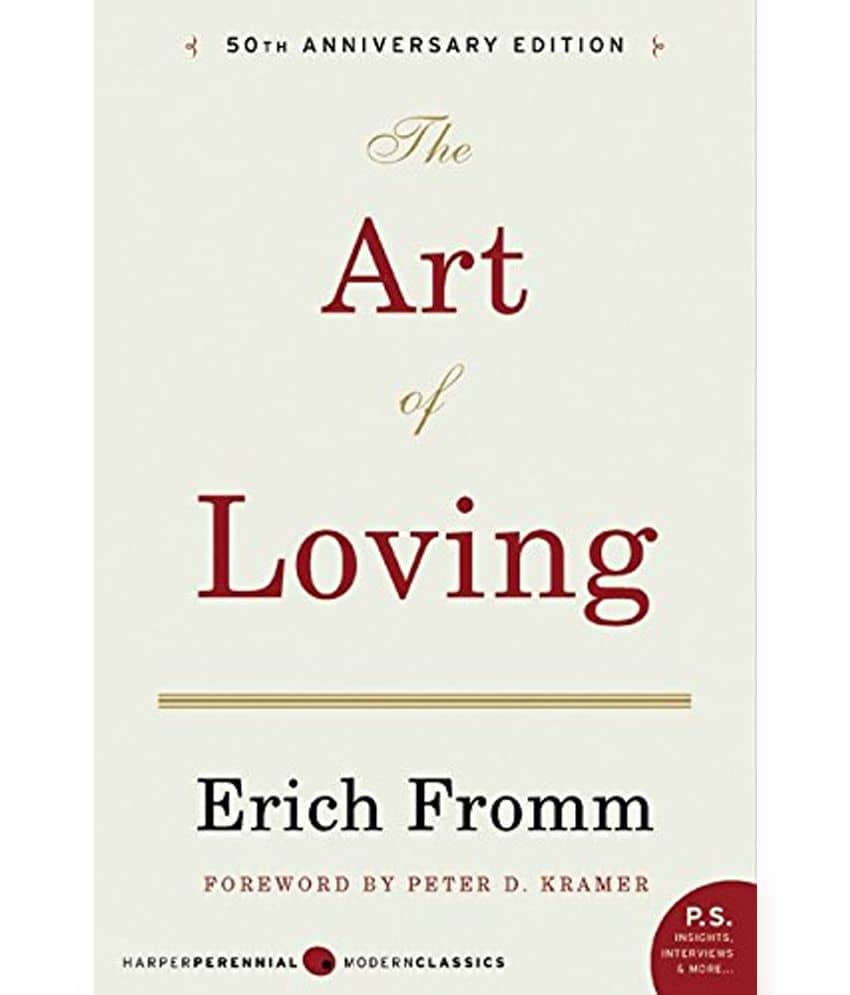
Mencintai adalah Sebuah Pekerjaan
30/11/2016
