Didik

Orang Yunani kuno biasa mengisi waktu luang mereka dengan mengunjungi sebuah tempat atau seseorang yang telah diakui kepandaiannya. Mereka datang untuk bertanya tentang aneka persoalan, baik terkait dengan ilmu praktis atau mistis. Aktivitas beranjangsana serta bertanya ini mereka namai dengan istilah skhole, scola, scolae, atau schola. Empat lema tersebut memiliki definisi sama: “waktu yang digunakan untuk belajar”.
Jauh sebelum aktivitas berdialog dan bertanya berkembang di masyarakat Yunani kuno, kegiatan serupa pernah dilakukan oleh bangsa Cina purba pada sekitar 2000 SM. Konon, itulah muasal sekolah tertua di dunia yang pernah diketahui hingga sekarang.
Di India, Kaum Brahmin juga pernah membangun “Sekolah-sekolah Veda” dalam kurun waktu yang hampir sama. Beberapa bangsa lain pun memiliki ritus pola pengasuhan anak dan lembaga sekolah yang berlainan ragam, bentuk, dan sifatnya.
Pada masa Yunani kuno, kegiatan bertanya tadi sepenuhnya milik para orang dewasa. Orang dewasa ini kemudian menitahkan anak-anak mereka, terutama anak laki-laki yang diharapkan dapat menggantikan peran ayahnya, untuk menjalani kebiasaan serupa.
Kemudian, gelombang kehidupan kian mendesak para orang tua ini. Mereka merasa tidak mampu memberikan pengajaran atas pelbagai hal kepada putra-putrinya sehingga mereka menitipkan putra-putrinya kepada seseorang yang “pandai”. Seseorang yang “pandai” ini, biasanya adalah mereka yang sebelumnya telah mengenyam skhole. Di tempat “penitipan” tersebut, anak-anak bermain dan belajar hal apapun yang mereka anggap mengasyikkan hingga tiba waktu mereka pulang kembali ke rumah.
Pola penitipan tersebut bernama scola in loco parentis, berarti lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah, sebagai pengganti “parentis” atau “ayah dan ibu”. Sesuai namanya, lembaga ini menggeser kedudukan lembaga sosialisasi tertua yang ada di dunia yaitu scola matterna (pengasuhan ibu sampai usia tertentu).
Tugas ibu lantas diperankan oleh dua subjek yang berbeda: orang tua kandung dari anak dan lembaga pengasuhan anak yang bukan orang tua kandung. Karena mengemban peran yang sama, kepada lembaga pengasuhan ini pun disematkan nama “ibu” yaitu “ibu asuh” atau “ibu yang memberikan ilmu pengetahuan”. Kita mengenalnya dengan istilah Alma Mater.
Kini, ketika garis waktu itu telah bergeser, kita akan mendapati lema sekolah diringkus menjadi sekadar nama dari sebuah lembaga pendidikan yang memenuhi prasyarat tertentu. Sekolah harus memiliki ini dan itu, apa dan anu, dan yang paling celaka: harus mengajarkan mata ilmu yang telah dibakukan.
Untuk lulus jenjang pertama, seseorang harus mengenyam ilmu-limu dasar yang serupa. Di jenjang berikutnya, ilmu dasar itu diberikan lagi dengan menambah beberapa penjelasan. Setelahnya, giliran ilmu lain yang diajarkan. Sekuens itu terus berlanjut sampai seseorang itu tadi lulus dan mendapatkan ijazah.

Setidaknya, ada dua masalah yang lahir dari kenyataan ini. Masalah pertama terletak pada keseragaman. Mereka yang masuk ke alam belajar jelas memiliki latar belakang, kebutuhan, dan cita-cita yang berbeda. Tapi, sekolah mengerdilkan spektrum identitas itu dalam kurikulum, pakaian, hingga idealisme yang seragam. Sehingga, alih-alih memenuhi dahaga cita-citanya, mereka yang masuk ke dalam sistem sekolah akan keluar dengan pola pikir yang seragam pula.
Masalah kedua dijelaskan apik oleh Paulo Freire dalam magnum opusnya, Pedagogy of the Oppressed. Dalam buku itu, Paulo mengindikasikan gejala fatalisme yang diidap oleh gaya pendidikan saat ini. Fatalisme adalah watak serba patuh sebagai hasil dari suatu situasi kesejarahan dan kemasyarakatan yang terjadi pada relasi antara guru-murid di institusi pendidikan.
Akibat fatalisme adalah berhenti mengucurnya keran dialog sebagai muruah sekolah yang sebenarnya. Pendidikan berubah menjadi ajang bercerita guru serta menekuk murid sebagai pendengar belaka. Murid, tak pelak, menjadi robot. Nasib mereka tak jauh beda bejana kosong yang minta diisi. Maka, ukuran keberhasilan pendidikan pun diterjemahkan menjadi sebagaimana berhasil guru mengisi bejana pikiran murid dan sebagaimana patuhnya bejana itu untuk diisi.
Dialog pun kian punah. Ruang gerak murid cuma berpendar antara menerima, mencatat, atau menyimpan. Daya cipta dan daya ubah mereka lumpuh. Padahal, kreasi adalah anugerah terbesar yang mampu keluar dari pemanfaatan akal.
Maka tak heran jika Ivan Illich, seorang filsuf Austria, dalam De Schooling Society menusukkan kritik pada sistem sekolah yang ada. Ivan menyatakan kalau sekolah di masa kini menuntut pengelolaan serupa sebuah korporasi demi menciptakan produk “murid” yang seakan unggul. Padahal, sebenarnya mereka seragam.
Sekolah, sebagai korporasi, menstempel para murid dengan ijazah seperti memberikan kode baris pada kaleng makanan. Demi penyesuaian kode baris itu, sekolah mengatur segalanya: administrasi, manajemen, proyeksi-proyeksi, rencana induk pengembangan, anggaran belanja, efisiensi, modal kerja, menakar kecenderungan arus penawaran dan permintaan, hingga merencanakan laba. Semua lelaku tadi bermuara agar ijazah yang dikeluarkan dianggap valid.
Validnya ijazah lalu berpengaruh lebih besar lagi. Ia dianggap sebagai tolok ukur. Nilai-nilai yang tercantum dalam ijazah menjadi kualifikasi awal manusia di mata masyarakat untuk melakukan peran tertentu. Mereka yang memiliki nilai tinggi dianggap “lebih cocok” bagi masyarakat, diakui kapabilitasnya, dan memiliki citra lebih pintar.
Padahal, jika hendak melongok lebih dalam, kumpulan ilmu yang dibekukan ke dalam pengajaran yang verbalistik justru melumpuhkan. Ilmu, yang seharusnya dicerap melalui dialog, justru dibopong jauh ke menara gading dan dikelola seperti pabrik. Manusia tidak berpikir lewat keterlibatan dengan realitas. Hasilnya, rangkaian pendidikan yang ada justru mengekang, alih-alih membebaskan.
Maka, peringatan tentang pendidikan seharusnya membawa kita membaca ulang sistem pendidikan yang ada. Apakah yang diajarkan dalam sekolah memang benar ilmu (logos) dan bukan sekadar mantra (doxa)? Atau, yang lebih penting, benarkah sistem pendidikan berupa sekolah masih membawa muruah pengasuhan sehingga mampu membuat manusia memenuhi fitrahnya: berpikir secara merdeka.
Karena, kau tahu, pendidikan tanpa kebebasan sebenarnya tak jauh nasibnya dengan apa yang biasa kau sebut dengan penjajahan.
Related
Melukis Kembali Gelap Terang Kartini
You May Also Like
Melukis Kembali Gelap Terang Kartini
25/04/2017
Gubahan Asik Piano Klasik Ista
03/11/2016
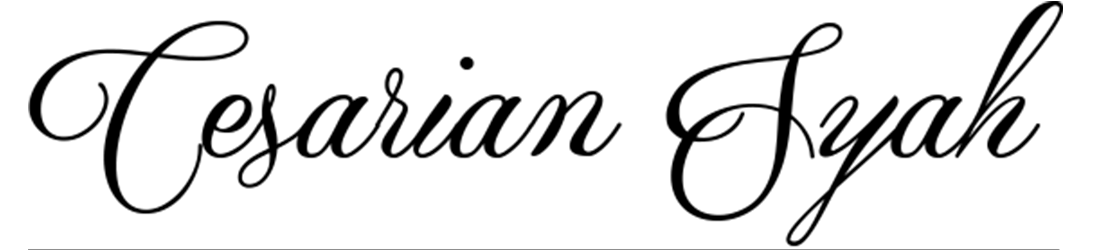
37 Comments
Irdinata Wijayanto
*sungkem pada guru
Meidiawan Cesarian Syah
wahahaha apaan nih mas kok sungkem-sungkem hahaha